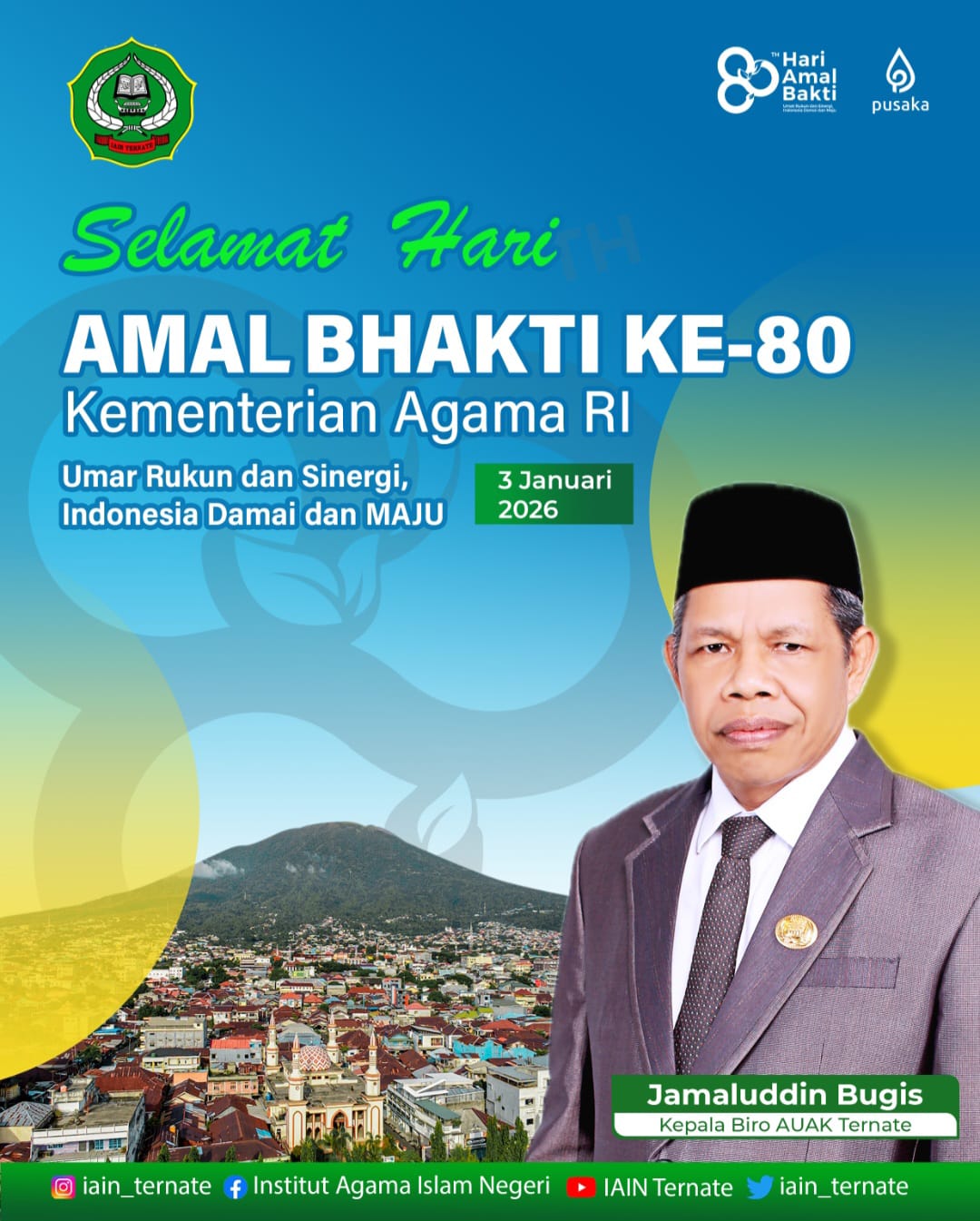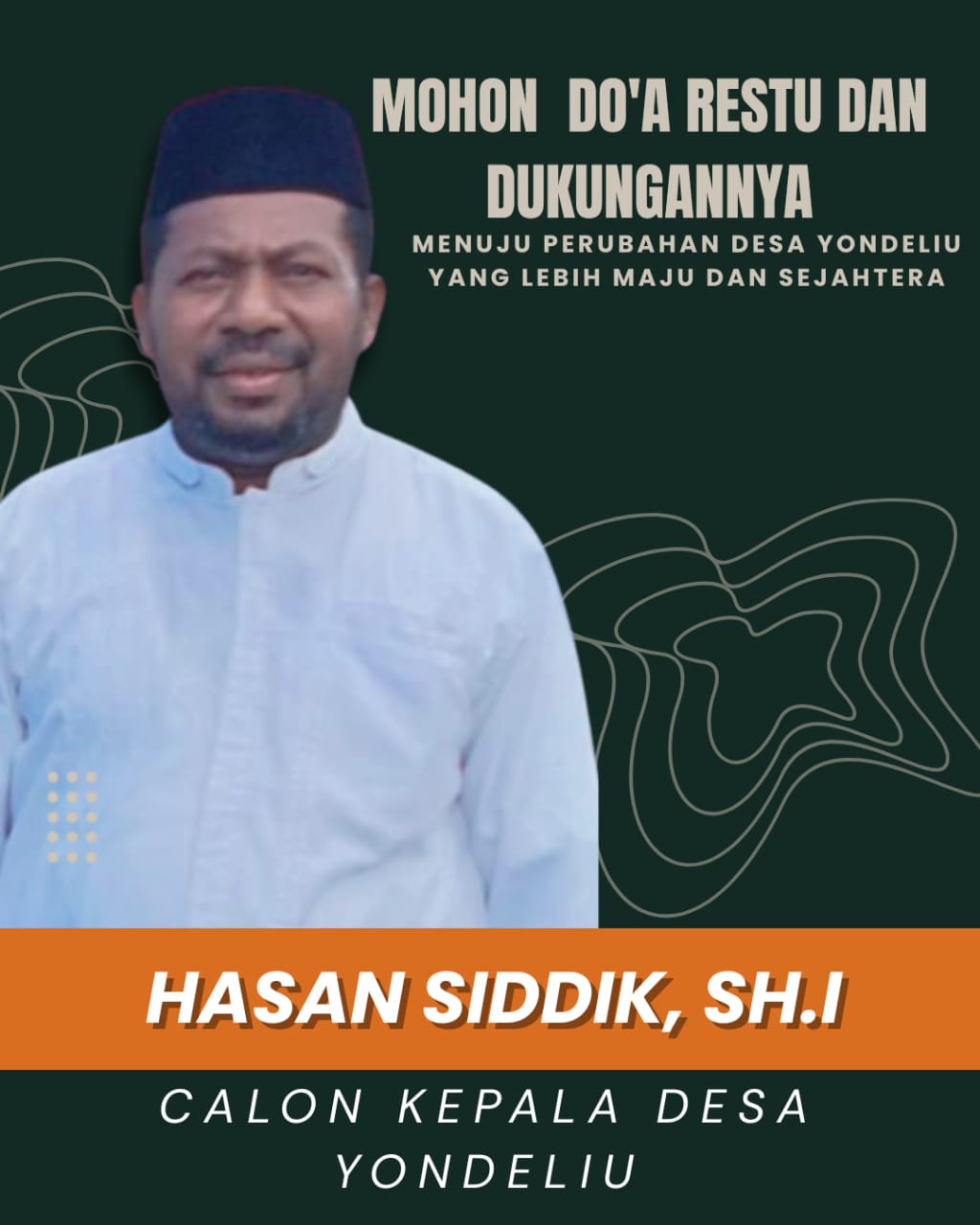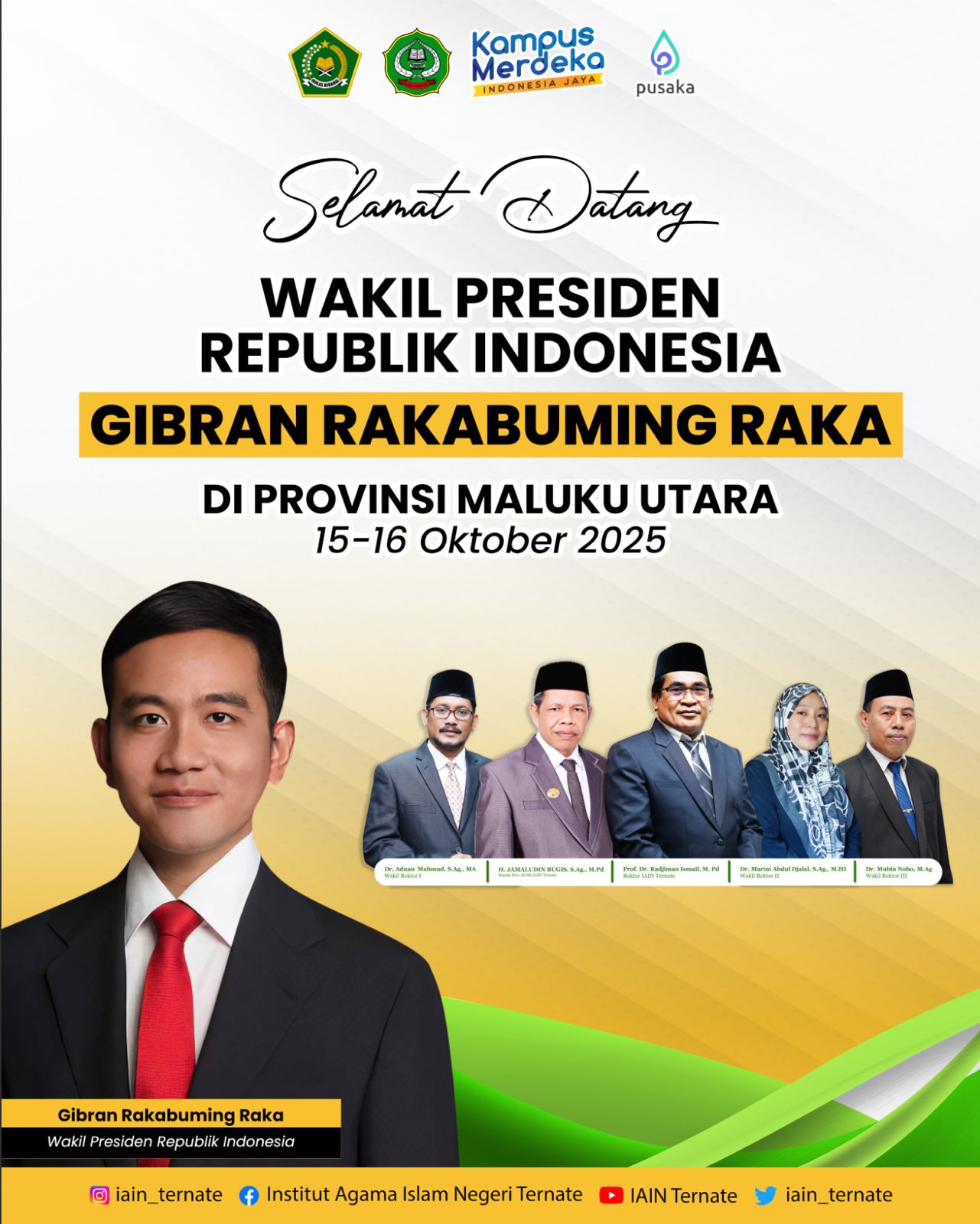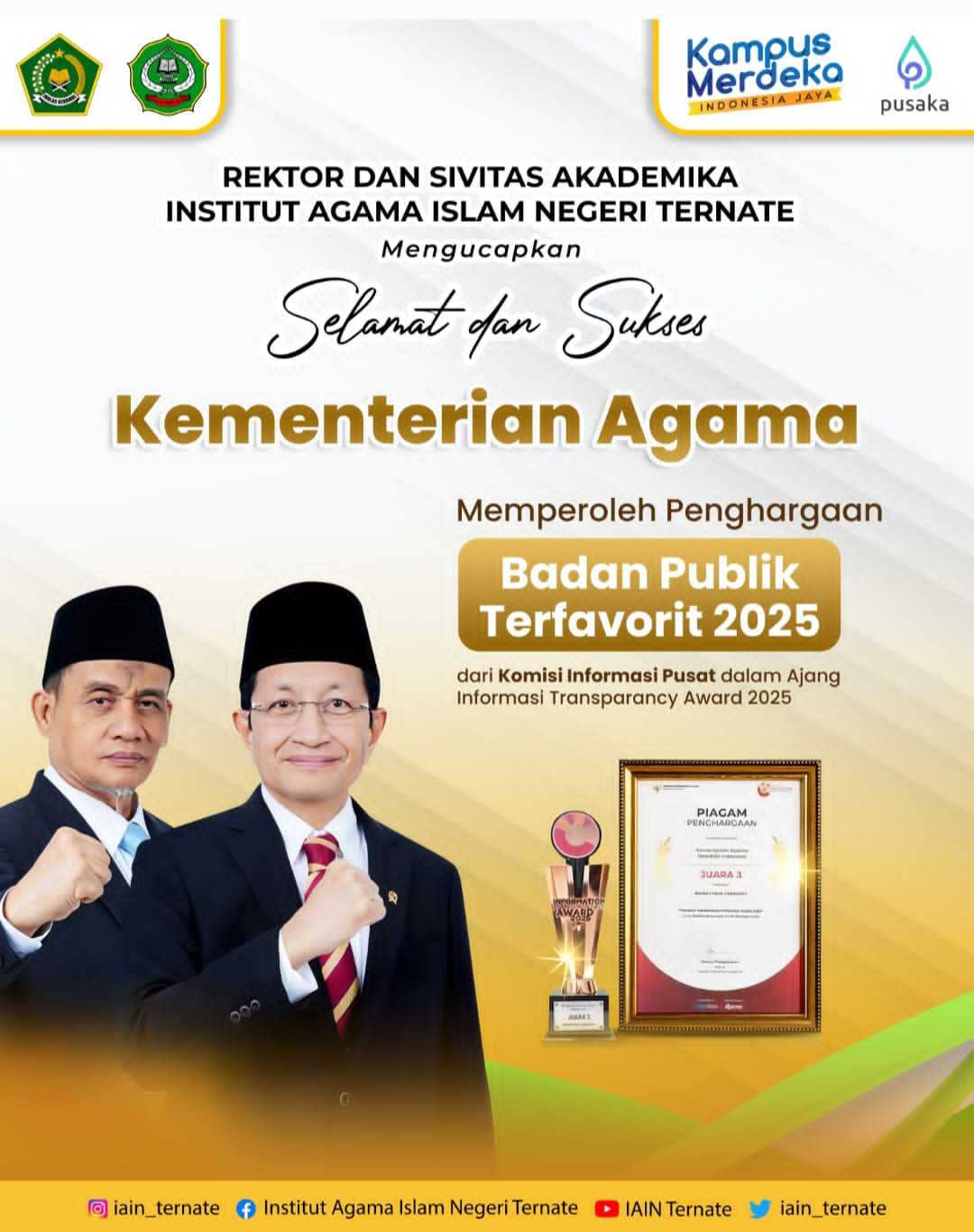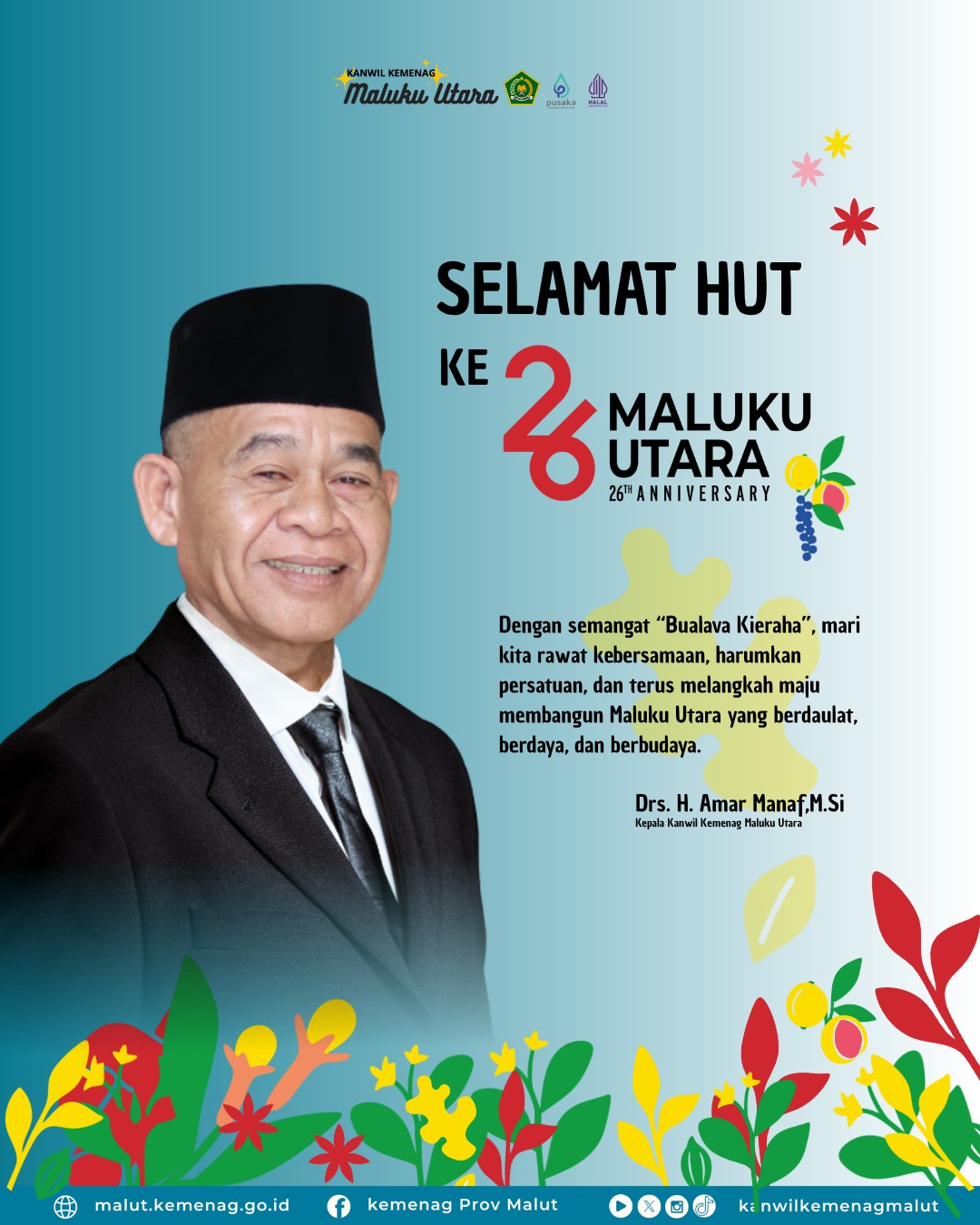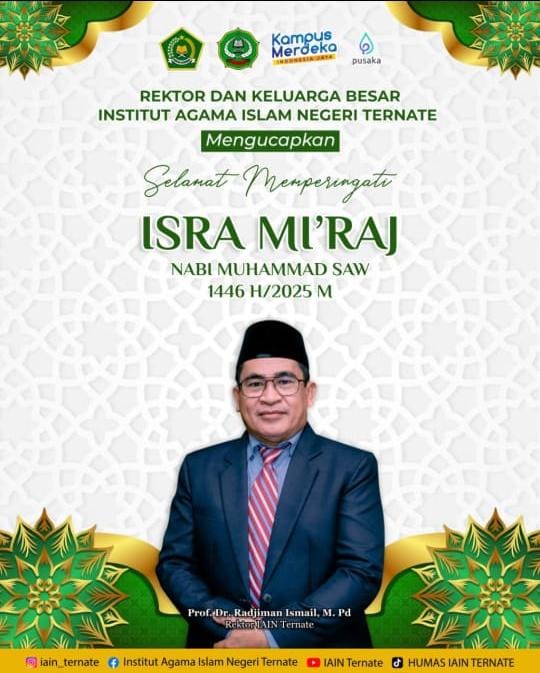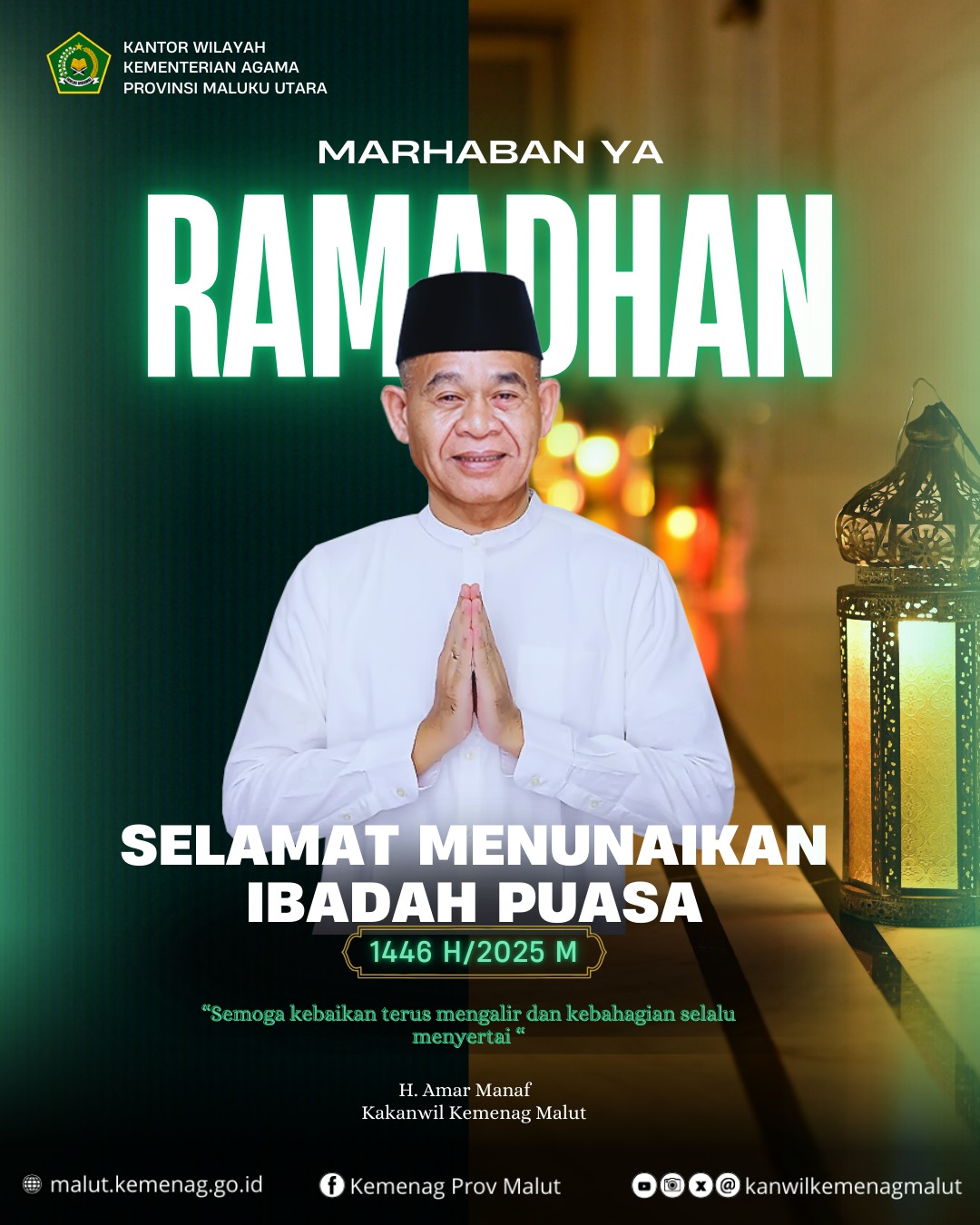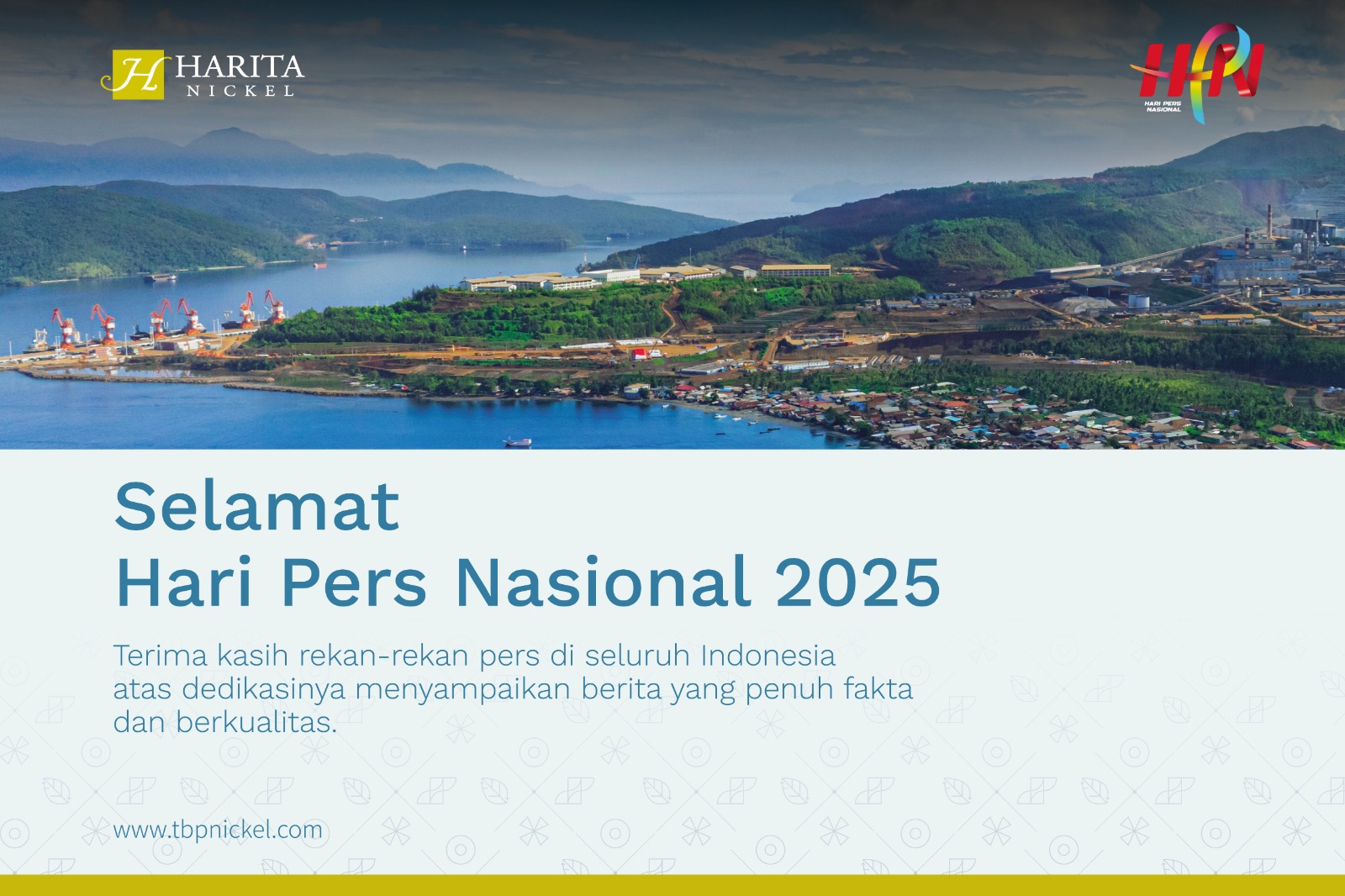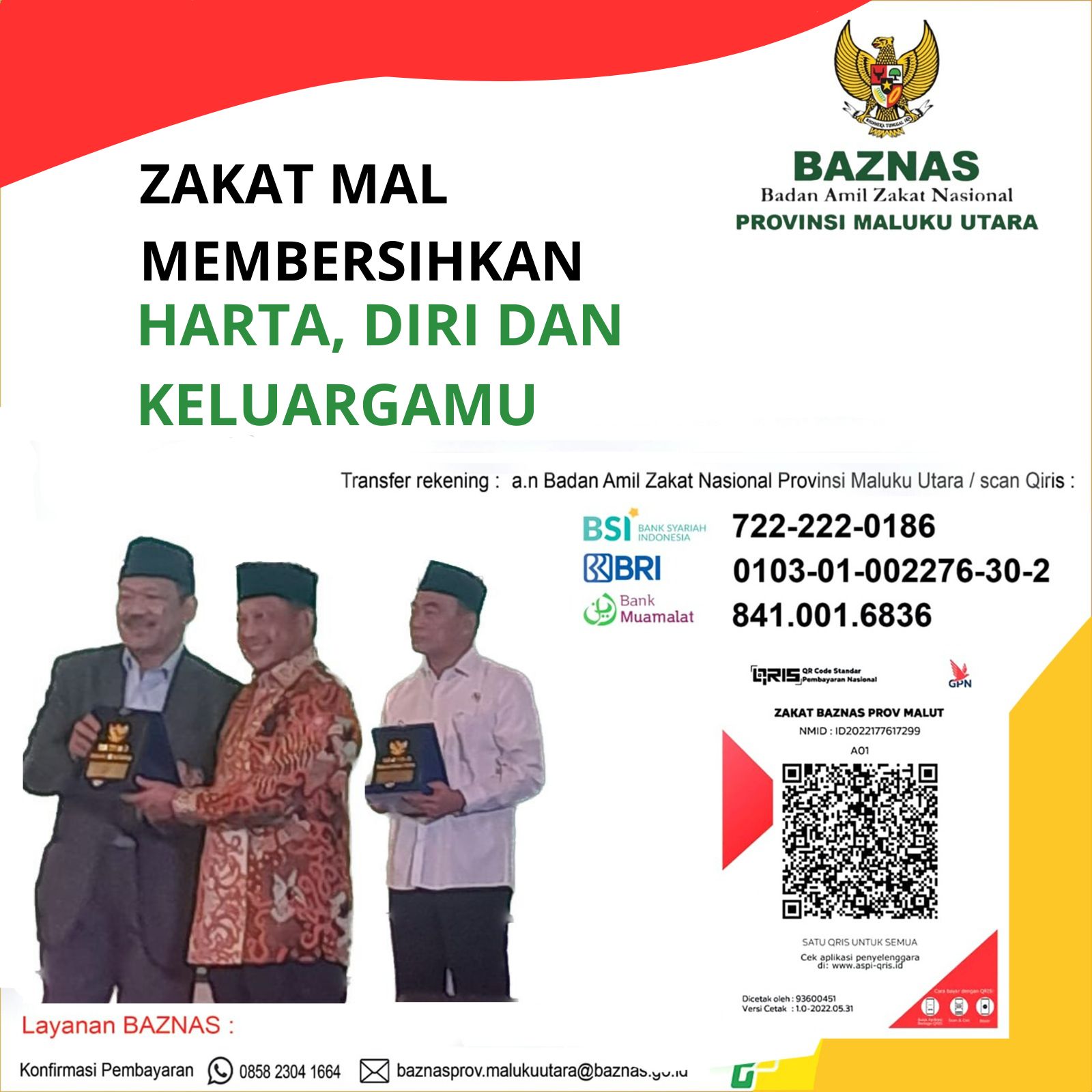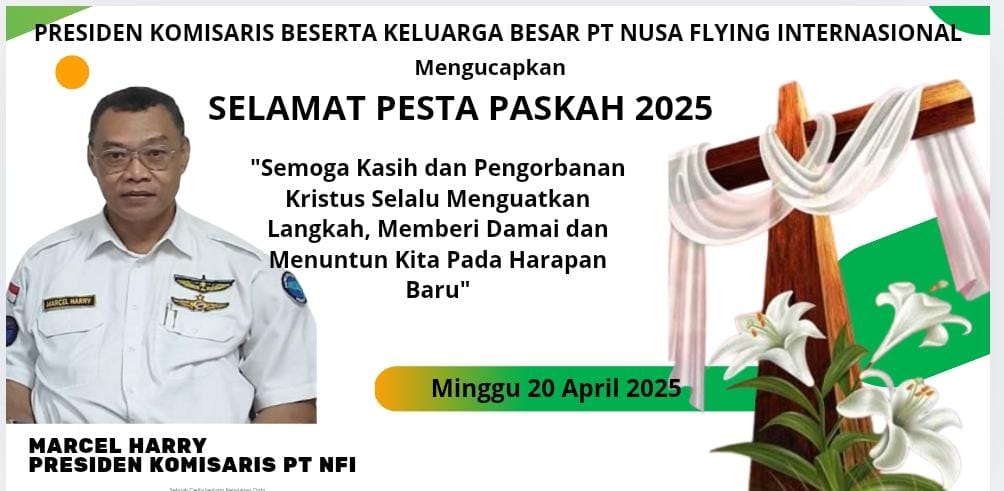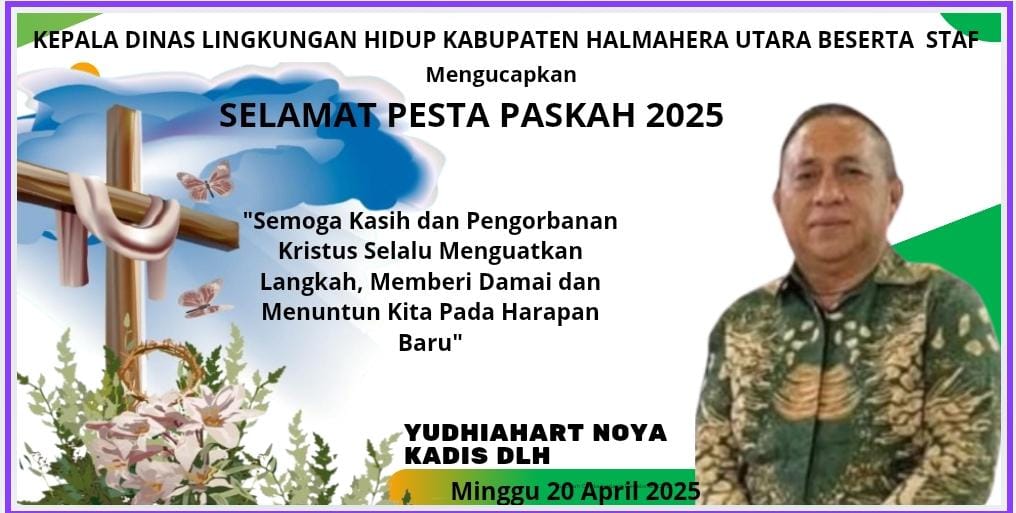DI INDONESIA, perjuangan kaum disabilitas untuk memperoleh hak yang setara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masih menemui banyak tantangan. Meskipun pemerintah telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan nasional, pelaksanaan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas belum sepenuhnya efektif. Kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih memerlukan perbaikan sistemik.
Indonesia telah meratifikasi _Convention on the Rights of Persons with Disabilities_ (CRPD) melalui UU Nomor 19 Tahun 2011. Komitmen ini diperkuat dengan diterbitkannya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini menjadi tonggak penting karena menggantikan UU Nomor 4 Tahun 1997 yang dianggap terlalu medik dan kurang menekankan pendekatan sosial terhadap disabilitas.
UU No. 8 Tahun 2016 memberikan jaminan hak yang luas bagi penyandang disabilitas, seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, perlindungan dari diskriminasi, dan partisipasi politik. Namun, realisasi dari hak-hak tersebut masih menghadapi kendala karena belum optimalnya peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah.
Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan disabilitas adalah minimnya anggaran dan rendahnya kapasitas institusi pelaksana. Data dari Kementerian Sosial (2022) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kabupaten/kota yang memiliki unit layanan disabilitas aktif dan memiliki staf terlatih. Bagaimana di Maluku Utara?
Di sektor pendidikan, misalnya, kendala terbesar adalah kurangnya guru pendamping khusus (GPK) dan fasilitas inklusif di sekolah-sekolah. Studi oleh Unicef dan Puslitjak Kemendikbudristek (2021) mencatat bahwa hanya 18% sekolah di Indonesia yang memiliki akses ramah disabilitas.
Sementara itu, dalam dunia kerja, meskipun UU No. 8/2016 mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan minimal 1% penyandang disabilitas dari total pegawai, pelaksanaannya belum optimal. Laporan ILO (2023) menyebutkan bahwa hanya 0,3% perusahaan di Indonesia yang benar-benar memenuhi kuota tersebut.
Meski demikian, terdapat sejumlah praktik baik dari pemerintah daerah. Ini perlu dicontoh. Misal, Kota Surakarta, dikenal sebagai kota inklusif yang menyediakan angkutan umum ramah disabilitas dan layanan terpadu. Inisiatif Disabilitas Center di Kota Semarang juga menjadi contoh bagaimana integrasi layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi penyandang disabilitas dapat berjalan baik dengan kemitraan multisektor (Menteri Sosial, 2022).
Bagi Kabupaten/Kota di Maluku Utara, integrasi layanan bagi kaum disabilitas belum terlihat.
Kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas harus dilihat sebagai bagian dari pembangunan manusia yang inklusif. Diperlukan keberpihakan nyata melalui anggaran, pelatihan SDM, pengawasan, dan partisipasi aktif komunitas disabilitas dalam perencanaan kebijakan.
Seiring dengan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju yang inklusif dan berkeadilan sosial, kesetaraan bagi penyandang disabilitas bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga komitmen moral dan politik seluruh pemangku kepentingan.
Kita berharap, Kabupaten/Kota di Maluku Utara mulai memperhatikan integrasi layanan yang inklusif bagi kaum disabilitas. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan.(*)