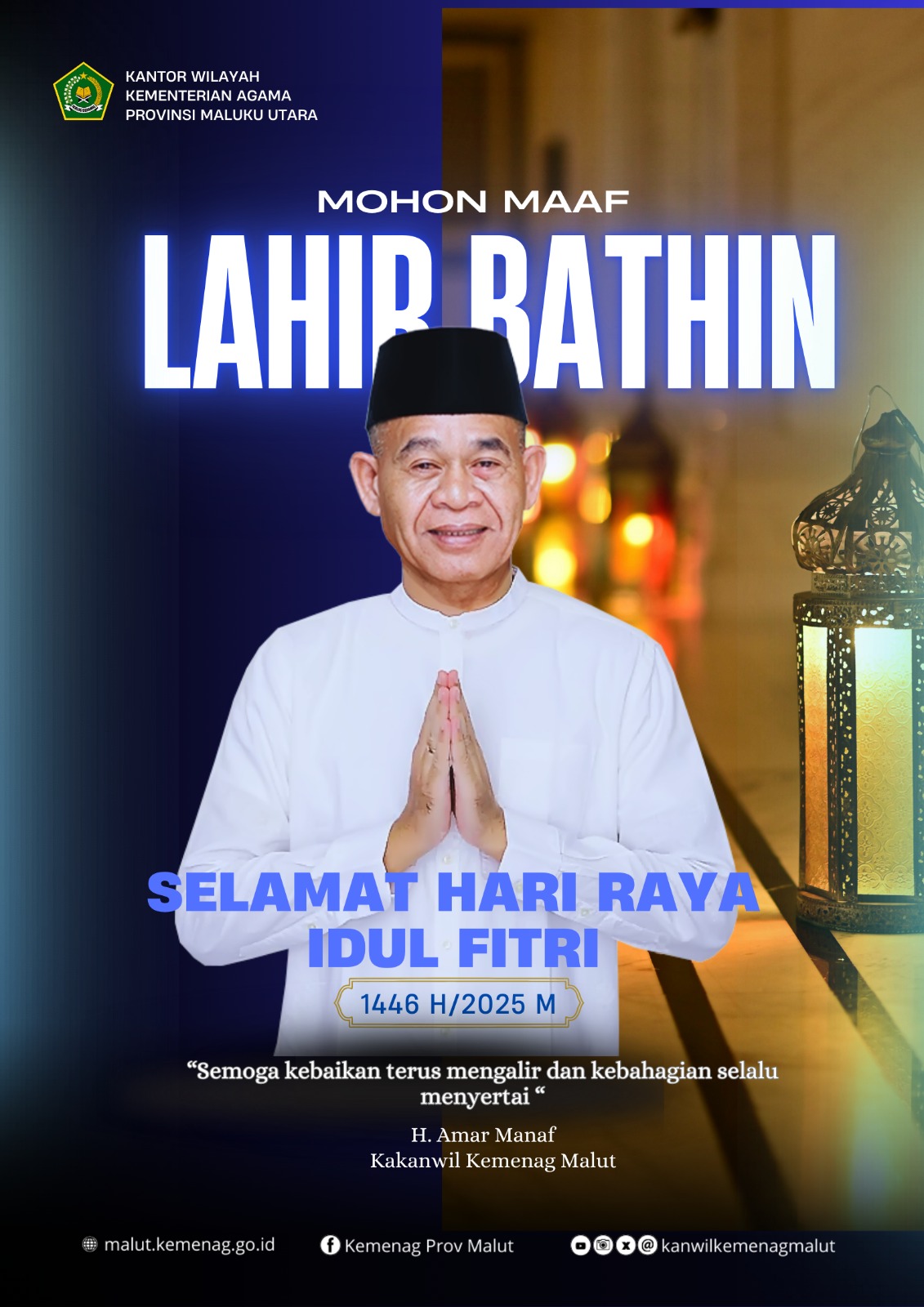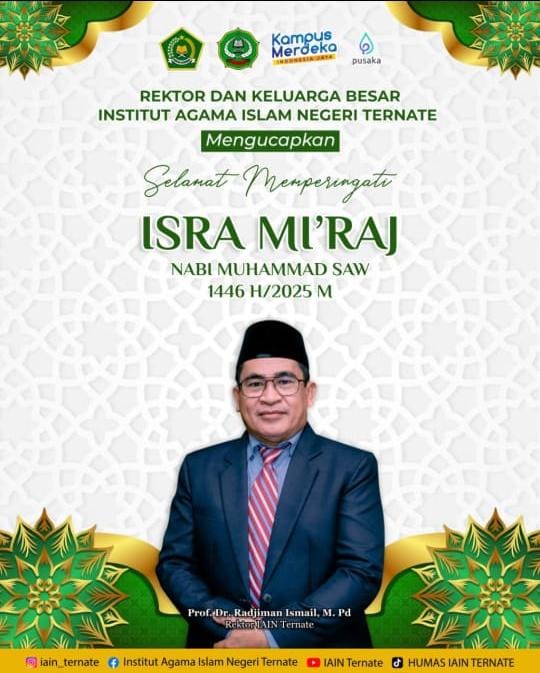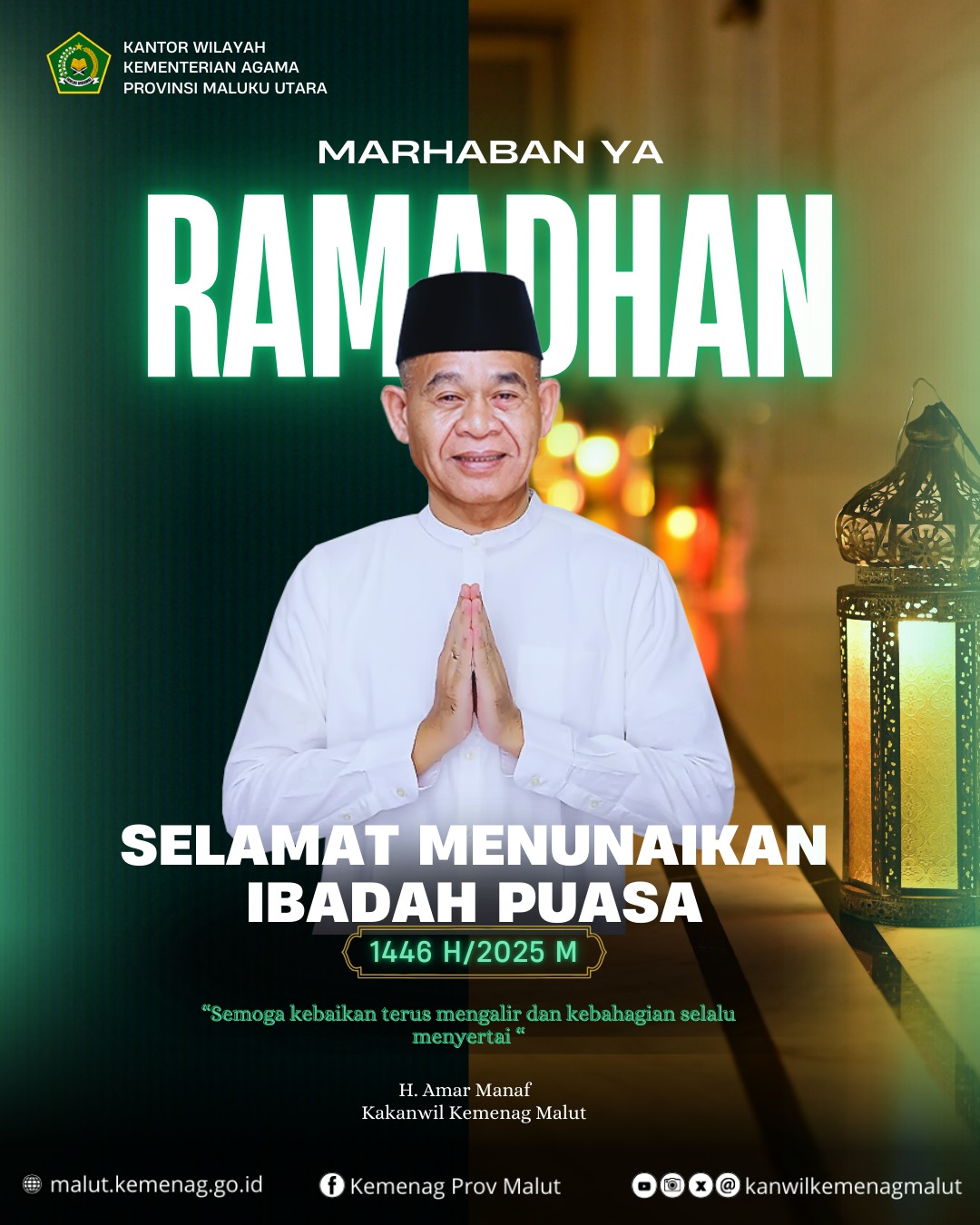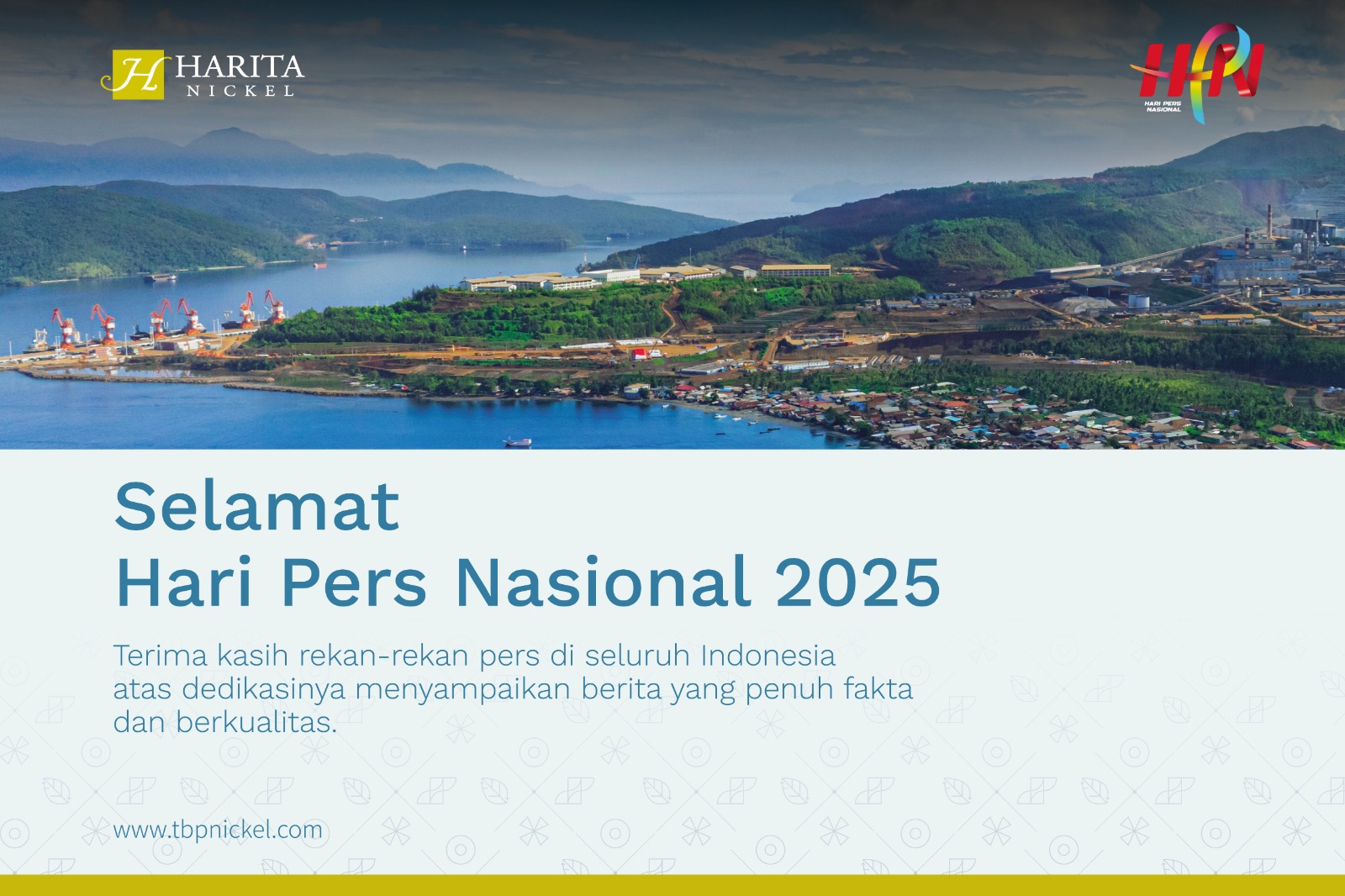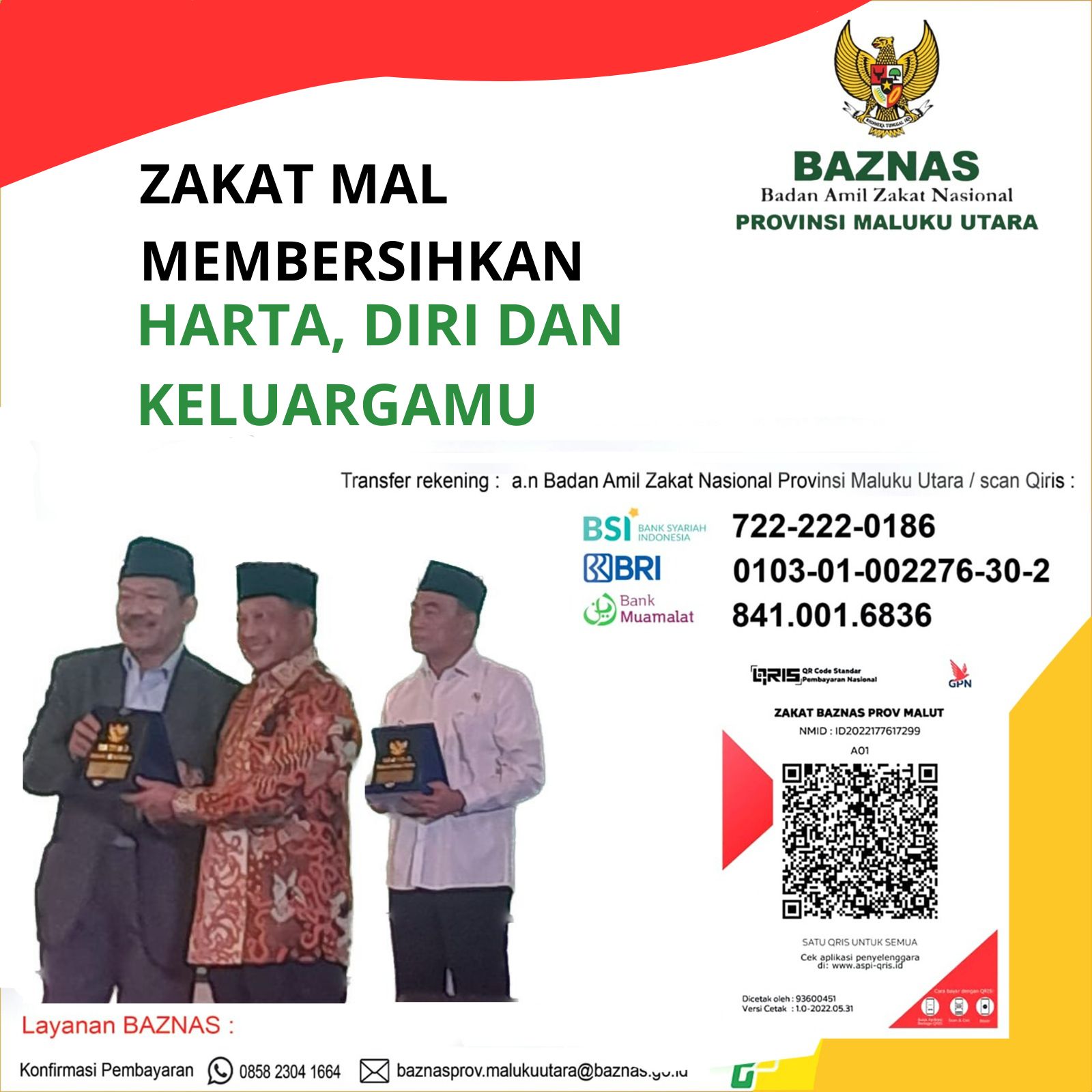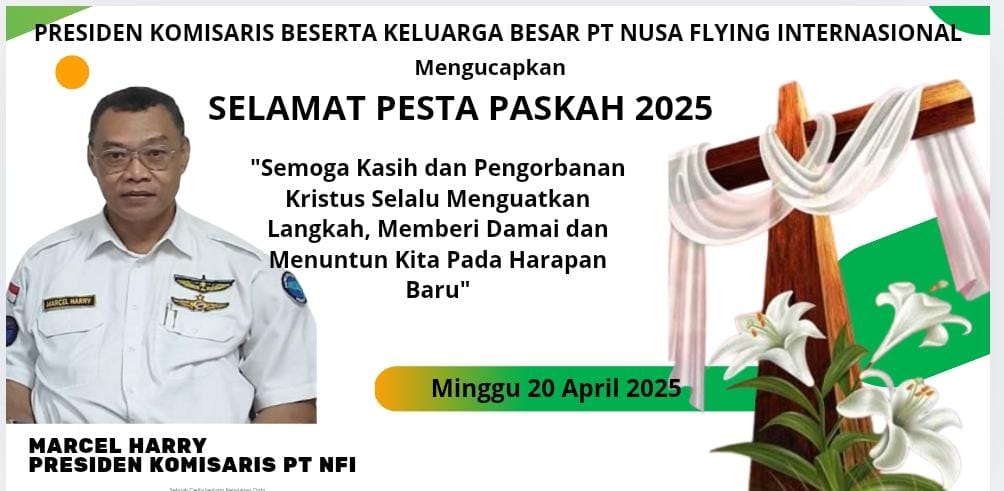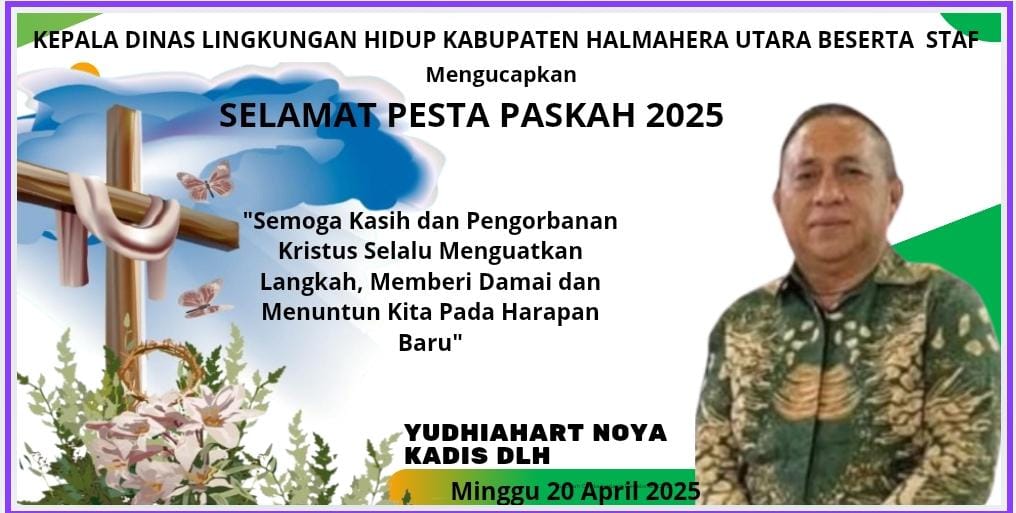POTENSI pangan lokal Maluku Utara menyimpan potensi besar untuk membangun ketahanan pangan dan energi secara berkelanjutan.
Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat, daerah ini sebenarnya memiliki modal yang kuat untuk keluar dari ketergantungan impor dan menghadapi tantangan krisis iklim serta ketimpangan ekonomi (Kominfo, 2022).
Kunci utamanya adalah pemanfaatan sumber daya lokal melalui pendekatan hilirisasi, teknologi tepat guna, serta pemberdayaan komunitas lokal secara terpadu (Nitami et al., 2023).
Salah satu contoh keberhasilan hilirisasi yang patut dicontoh adalah inovasi Dewacoco di Halmahera Barat. Melalui pemanfaatan limbah sabut kelapa sebagai energi biomassa menggunakan teknologi gasifikasi, limbah tersebut berhasil diubah menjadi briket, syngas ( energi bersih), dan biochar untuk rehabilitasi tanah.
Model industri ini tidak hanya mengurangi polusi dan meningkatkan nilai tambah kelapa, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan petani lokal. Hal ini membuktikan bahwa industri kelapa di Maluku Utara tidak hanya berorientasi pada ekspor, namun juga mampu menjadi penggerak kemandirian energi dan pembangunan hijau (Murdani, 2025).
Dalam sektor pangan, pemanfaatan lahan tidur menjadi solusi nyata yang telah terbukti di beberapa wilayah, seperti di Ternate. Hasil panen dari lahan- lahan yang sebelumnya tidak tergarap menunjukkan potensi besar, di mana bawang saja mampu menghasilkan 1 ton dalam satu kali panen (Rima, 2024).
Di sisi lain, sektor perikanan juga menyimpan potensi besar dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, penertiban terhadap praktik ilegal seperti rompong ilegal oleh oknum luar daerah sangatlah penting. Selain itu, dukungan alat tangkap modern dan kemudahan pengajuan rumpon bagi nelayan lokal akan memperkuat ketahanan sektor ini (Fatah, 2022).
Lebih jauh lagi, Maluku Utara memiliki tiga komoditas unggulan yang sangat strategis, sagu, cengkih- pala, dan hasil perikanan. Menurut Silalahi, (2024) Sagu memiliki potensi besar sebagai sumber pangan alternatif, mengingat Indonesia memiliki lahan sekitar 5,5 juta hektar sagu yang tersebar di berbagai daerah dimana di Maluku Utara sendiri memiliki 4.360 ha.
Namun, hingga kini, pemanfaatannya masih sangat minim, yaitu baru sekitar 5% yang telah digunakan secaraoptimal, padahal sagu memiliki potensi besar untuk menggantikan beras sebagai sumber karbohidrat lokal. Sagu juga lebih tahan terhadap perubahan iklim (Andri, 2024).
Sementara itu, menurut Hanifah & MAlik, (2020) perkebunan dan pertanian dimana didalamnya terdapat cengkih dan pala yang memberikan kontribui 20% terhadap PDRB. Pala dan cengkih sebagian besar masih diekspor dalam bentuk mentah (Aminuddin, 2019). Padahal, hilirisasi produk rempah Maluku Utara akan meningkatkan nilai ekspornya (Fatah, 2023).
Maluku Utara adalah provinsi kepulauan dengan komposisi wilayah yang didominasi oleh laut, yakni sekitar 79%, sementara daratannya hanya mencakup 30%. Provinsi ini termasuk dalam empat Wilayah Pengelolaan Perikanan ( WPP), yaitu WPP 714, 715, 716, dan 717, dengan potensi sumber daya perikanan yang mencapai 1,4 juta ton setiap tahunnya (Kominfo, 2022).
Sektor perikanan, Produksi perikanan Maluku Utara pada tahun 2022 tercatat mencapai 378.111 ton, melebihi target sebesar 356.400 ton atau setara 106% (Ambari, 2023). Sdangkan pada tahun 2023 menurut kominfo dan 2025 berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, maluku utara memiliki estimasi potensi tangkapan ikan masng-masing sebesar 1,4 ton dan 715.293 ton (KKP, 2025).
Namun perbedaan pencapaian dan potensi ini menyisakan ironi karena di tengah melimpahnya potensi sumber daya ikan (SDI), justru belum sepenuhnya dioptimalkan hail kekayaan laut tersebut. Belum lagi terdapat Sebagian besar rumpon ilegal yang ditemukan di perairan Maluku Utara berasal dari nelayan provinsi tetangga, seperti Maluku dan Sulawesi Utara (Ichi, 2023).
Kehadiran rumpon- rumpon ini tidak hanya mengganggu aktivitas nelayan lokal, tetapi juga mengancam hilangnya sumber daya laut dan perikanan di wilayah tersebut. Selain itu, kapal ikan asing berbendera Filipina turut mengirimkan situasi dengan modus keluar masuk perbatasan di Samudera Pasifik dan secara diam- diam memasang rumpon di wilayah perbatasan, yang tentu saja melintasi perbatasan dan merusak ekosistem laut (Harianto, 2025).
Masalah lainnya adalah infratruktur nelayan contohnya Desa- desa di Kabupaten Kepulauan Morotai, Maluku Utara, dikenal sebagai penghasil ikan tuna, khususnya tuna sirip kuning, yang ditangkap secara tradisional dan kini semakin diminatipasar internasional, terlihat dari tren ekspor yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir (Ichi, 2025).
Namun, di balik potensi besar tersebut, kondisi infrastruktur nelayan masih jauh dari memadai. Oleh karena itu, Sekti menekankan penyediaan kapal penangkapikan yang lebih modern serta pembangunan industri penangkapan yang berkualitas, guna meningkatkan produksi, membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat dan daerah pada umumnya (Nurdin, 2025).
Dalam menjawab tantangan ini, teknologi menjadi solusi kunci (Kominfo, 2022). Peningkatan hilirisasi pangan maritim bertujuan untuk memberikan nilai tambah pada produk perikanan dan hasil laut sebelum dipasarkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.
Berbagai langkah strategi dapat dilakukan, mulai dari pembangunan infrastruktur pengolahan seperti pabrik, gudang pendingin, dan fasilitas pengepakan, hingga perbaikan sistem logistik dan transportasi. Adopsi teknologi modern dalam proses pengolahan, seperti pengeringan, pembekuan, dan pengalengan, juga penting untuk meningkatkan kualitas produk.
Selain itu, pelatihan kepada nelayan dan tenaga kerja terkait teknik pengolahan dan manajemen usaha menjadi kunci dalam meningkatkan standar produksi. Dukungan dari pemerintah dan sektor swasta melalui kemitraan, pembiayaan, dan insentif juga sangat diperlukan.
Diversifikasi produk olahan, seperti nugget, sosis ikan, serta makanan laut siap saji, dapat memperluas pasar domestik dan internasional, apalagi didukung oleh sertifikasi mutu seperti HACCP dan MSC yang meningkatkan daya saing.
Sebagaimana dijelaskan diatas dengan optimalisasi lahan sagu dan pengolahan produk turunan pala dan cengkih serta pengembangan produk agroforestri (perkebunan/pertanian berbasis campuran) contohnya cengke dan pala di barengi dengan tanaman lainnya atau tanaman pangan lainnya, solusi integratif semacam ini tidak hanya memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi daerah, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya lokal.
Tentunya dengan cara mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan dari segi produksi hingga distribusi dan permodalan yang efektif serta keberpihakan pemerintah agar berjalan dengan baik.
Sehingga bisa dilakukan kebijakan dengan membatasi inpor agar tidak ada lagi ketergantungan pangan dari daerah lain dengan mengkonsumsi hasil alam sendiri, dan bisa melakukan inpor saat adanya kekurangan pangan dengan catatan mengukur berapa persen kebutuhan inpor yang tidak mampu dipenuhi oleh hasil alam sendiri, mialnya 20% dari inpor dan 80% dari pangan sendiri dan sebaliknya Maluku Utara bisa melakukan ekspor jika kebutuhan dalam negerinya telah terpenuhi, sehingga Maluku Utara dapat mewujudkan kemandirian pangannya.
Ketahanan pangan yang kuat di Maluku Utara tidak hanya menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam menekan tingkat inflasi daerah. Dengan mengurangi ketergantungan pada impor dan mengoptimalkan produksi lokal, fluktuasi harga pangan dapat lebih stabil.
Selain itu, pengembangan sistem pangan berbasis potensi lokal menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, perikanan, dan pengolahan hasil pangan, sekaligus meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui diversifikasi dan inovasi produk. Dampak positif ini akan memperkuat fondasi perekonomian daerah secara berkelanjutan.
Penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis pangan lokal menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif di Maluku Utara. Dengan memberdayakan pelaku usaha lokal untuk mengolah dan memasarkan produk pangan asli daerah seperti sagu, pala, atau ikan tuna, perputaran ekonomi dapat lebih merata di tingkat masyarakat.
Dukungan berupa akses permodalan, pelatihan teknologi, dan perluasan pasar akan meningkatkan daya saing UMKM, sehingga tidak hanya meningkatkan pendapatan pelaku usaha tetapi juga memperkuat identitas dan kemandirian pangan daerah secara menyeluruh.
Langkah Taktis Pengembangan
Diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal menjadi solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan Maluku Utara pada beras impor sekaligus mengoptimalkan potensi pangan daerah.
Dengan mengembangkan alternatif sumber karbohidrat seperti sagu, umbi-umbian, dan pisang, serta mempromosikan pola konsumsi yang beragam, masyarakat dapat memiliki ketahanan pangan yang lebih baik.
Pendekatan ini tidak hanya memperkaya gizi tetapi juga melestarikan kekayaan biodiversitas lokal yang selama ini belum tergarap maksimal. Pemerintah daerah perlu mendorong inisiatif ini melalui kampanye edukasi dan insentif bagi petani pengembang komoditas alternatif.
Peningkatan teknologi pengolahan dan penyimpanan pangan merupakan faktor kunci dalam memperpanjang usia simpan produk lokal dan meningkatkan nilai ekonominya. Investasi pada teknologi sederhana seperti pengeringan, fermentasi, dan pengemasan vakum dapat membantu petani dan nelayan mengolah hasil panen mereka menjadi produk bernilai tinggi.
Pelatihan teknis bagi UMKM tentang good manufacturing practices dan penerapan cold storage system untuk pendingin akan meminimalisasi kehilangan pasca panen. Langkah ini sekaligus membuka peluang ekspor produk olahan khas Maluku Utara.
Membangun sinergi kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam rantai pasok pangan menjadi tulang punggung sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi ini dapat diwujudkan melalui kemitraan hilirisasi produk, pembentukan sentra distribusi terpadu, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
Peran swasta dalam investasi teknologi dan pemasaran perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang pro-bisnis, sementara masyarakat diajak berperan aktif melalui kelompok tani dan koperasi produsen. Model kemitraan tridaya ini akan menciptakan ekosistem pangan yang lebih efisien, adil, dan menguntungkan semua pihak.
Stabilitas ekonomi Maluku Utara dapat diwujudkan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam dan kearifan lokal untuk membangun ketahanan pangan yang mandiri. Dengan mengedepankan strategi diversifikasi pangan berbasis komoditas lokal seperti sagu, pala, umbi-umbian, dan pisang serta hasil perikanan, serta memperkuat infrastruktur pendukung, daerah ini dapat secara signifikan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi faktor krusial dalam menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.
Keberhasilan jangka panjang memerlukan implementasi kebijakan berbasis data dan pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh. Dengan memberdayakan pelaku UMKM melalui akses permodalan, pelatihan teknologi, dan penguatan rantai pasok, Maluku Utara tidak hanya mampu mencapai kemandirian pangan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan berbasis bukti dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan akan menjadi pondasi kokoh bagi terciptanya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di wilayah kepulauan ini.(*)