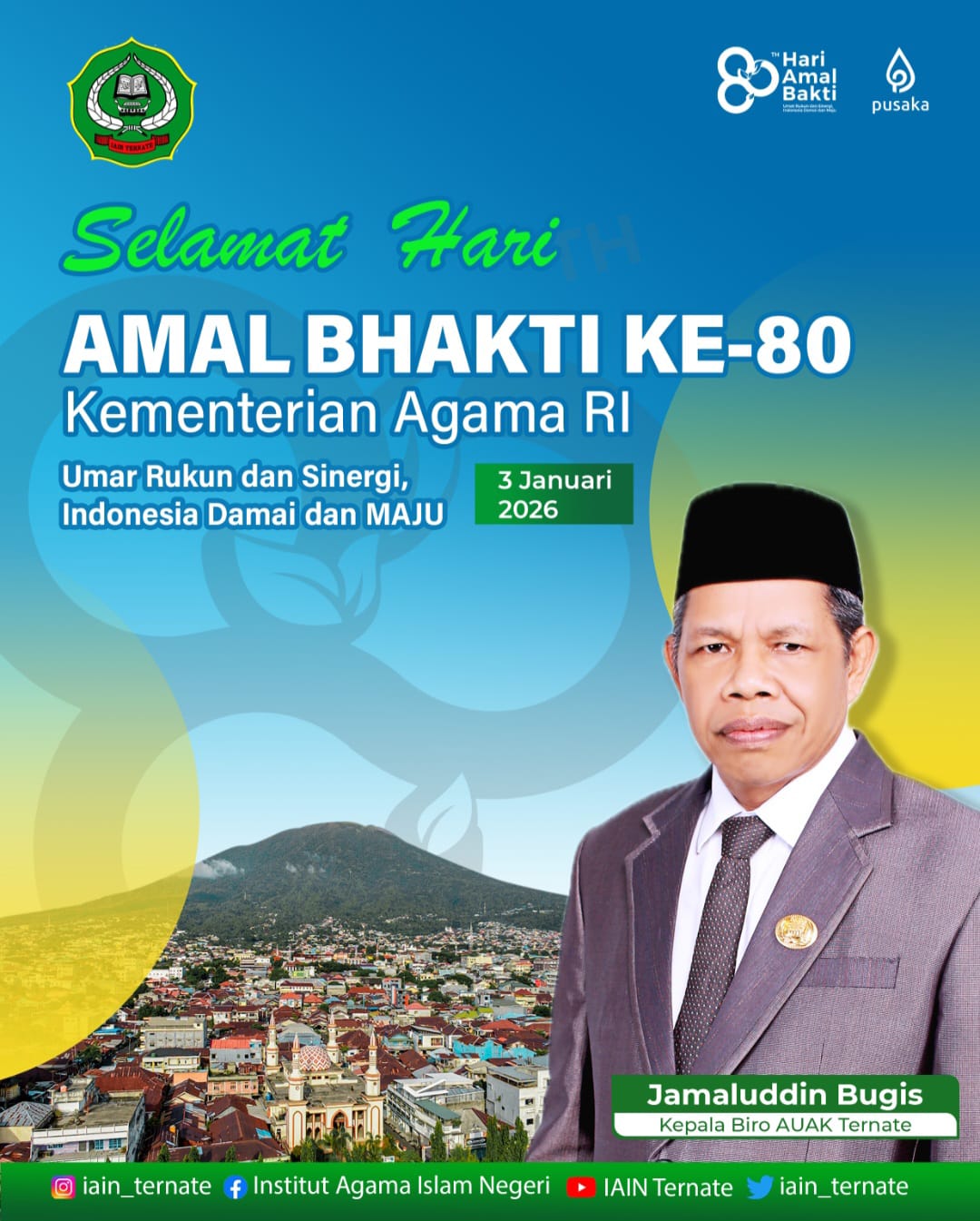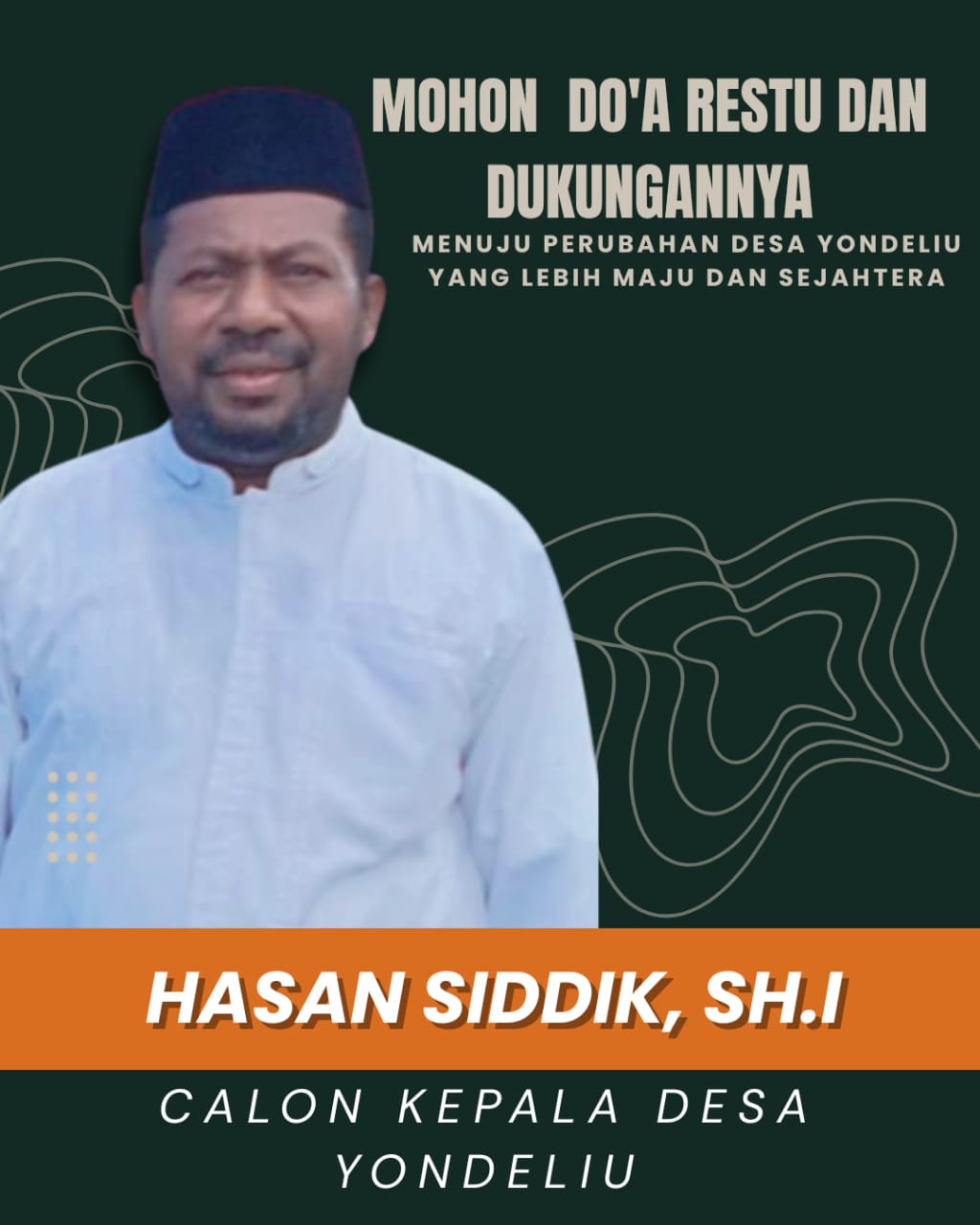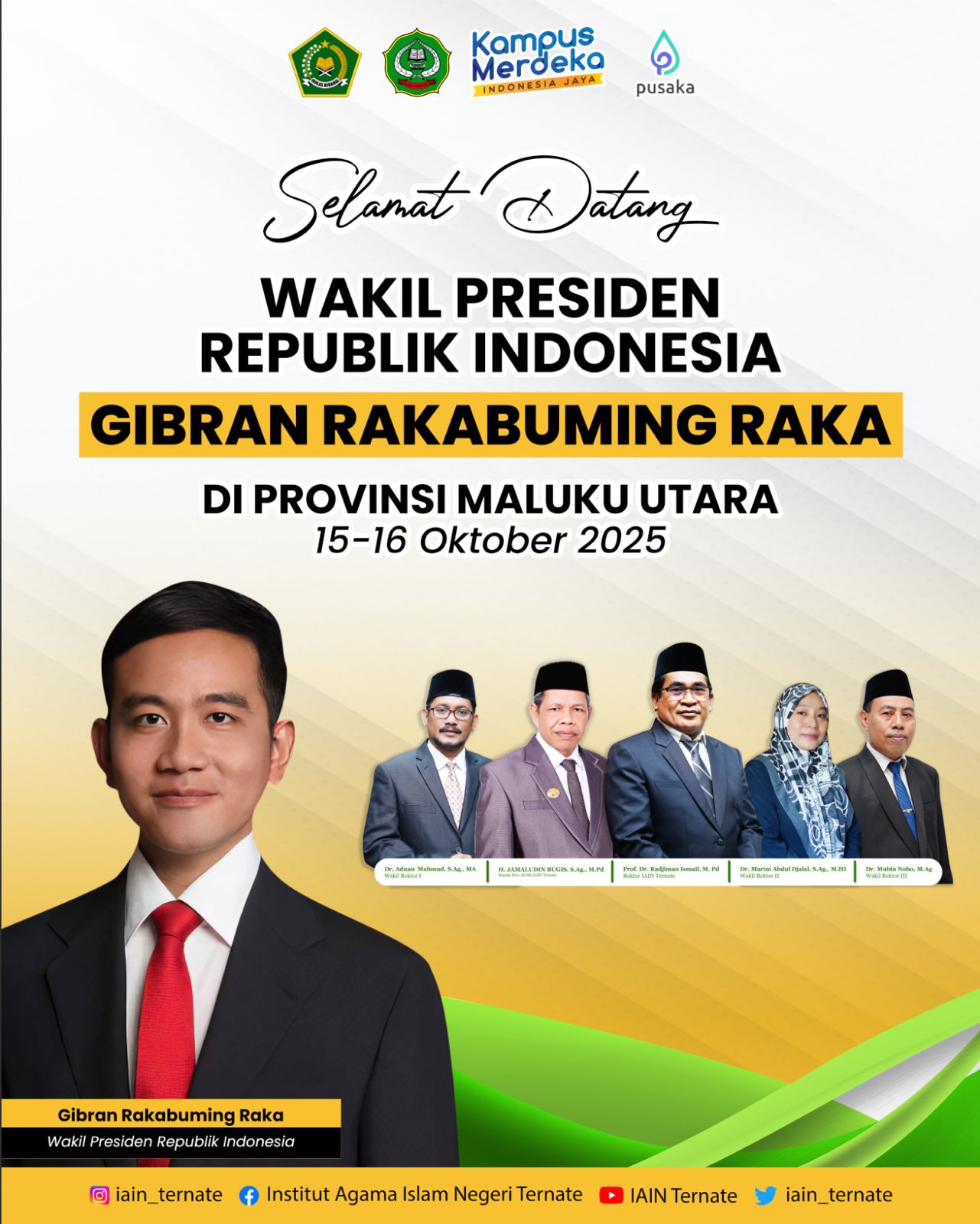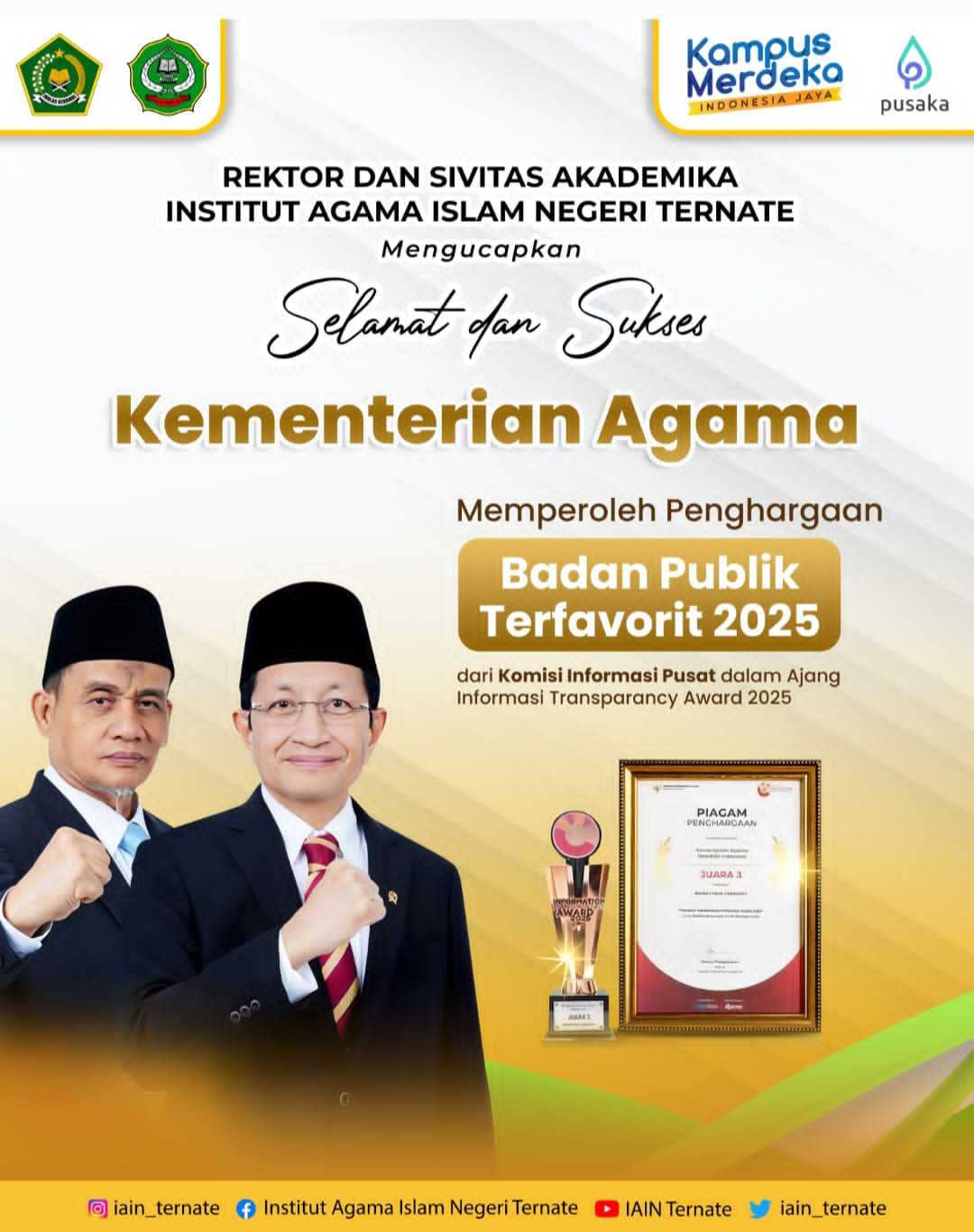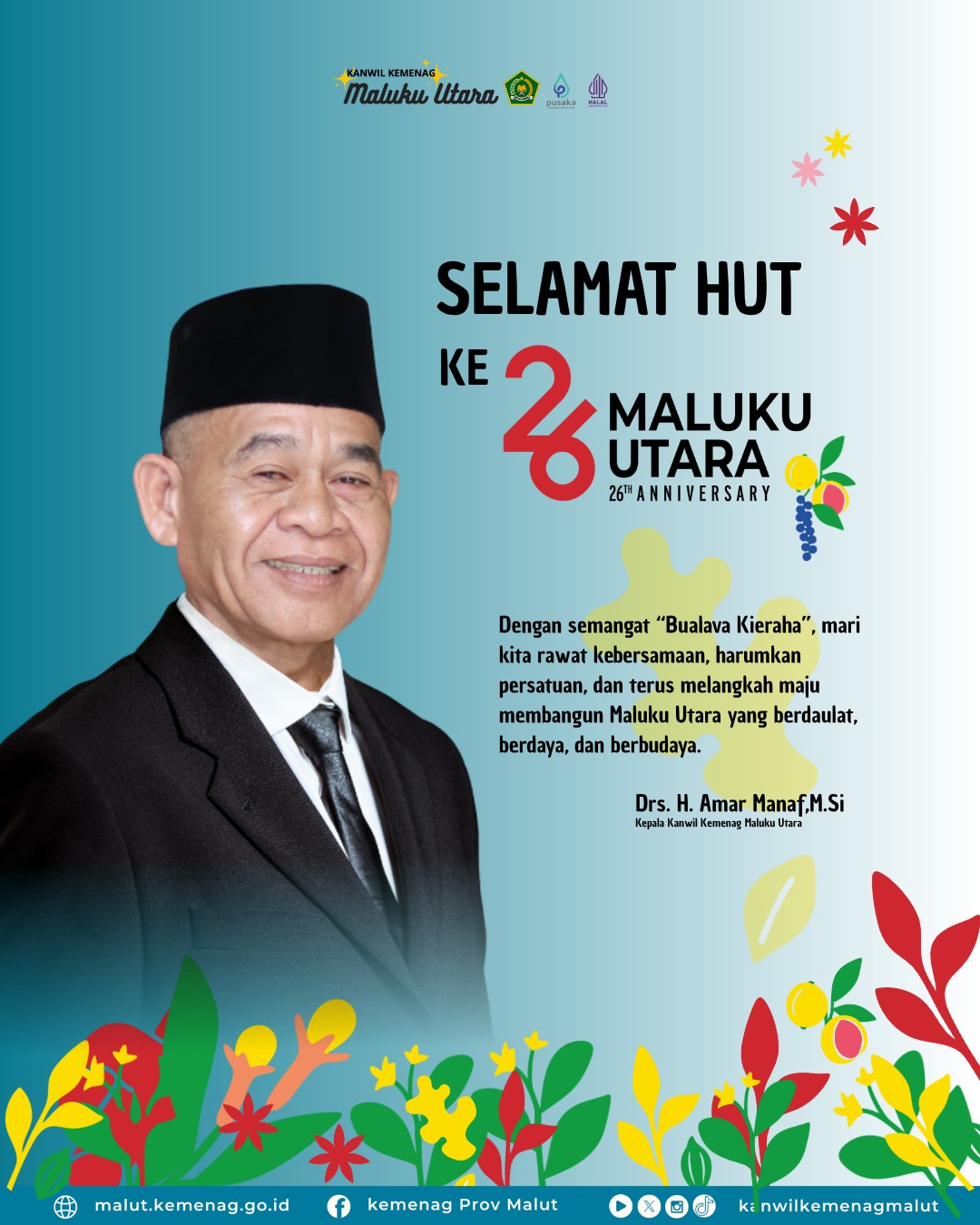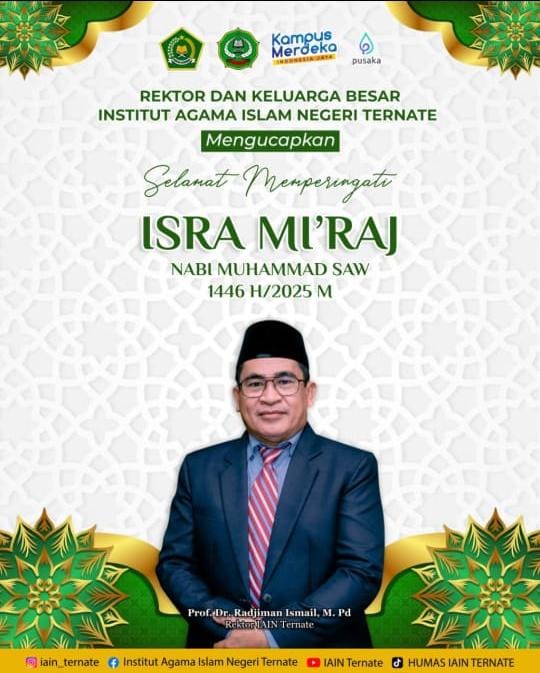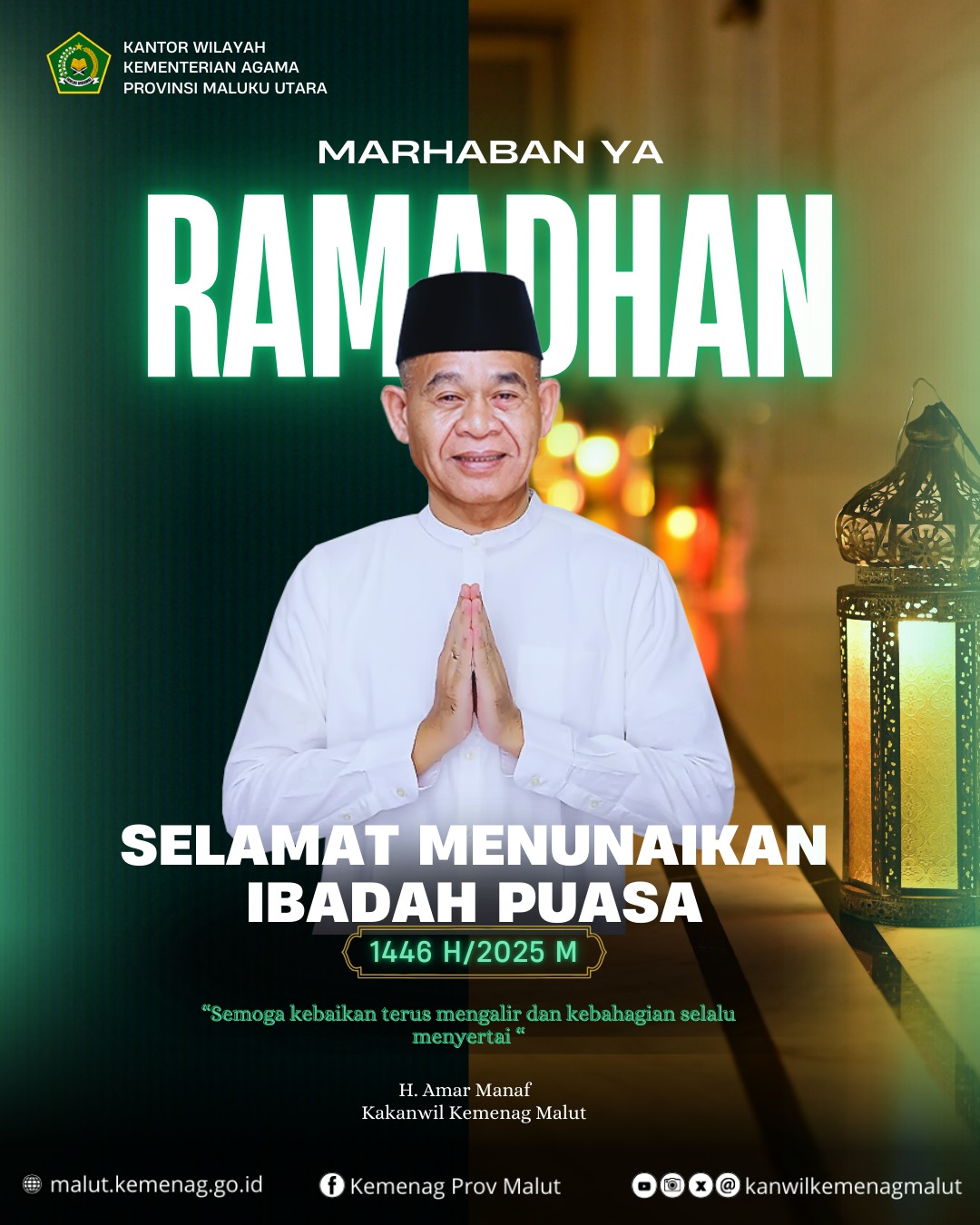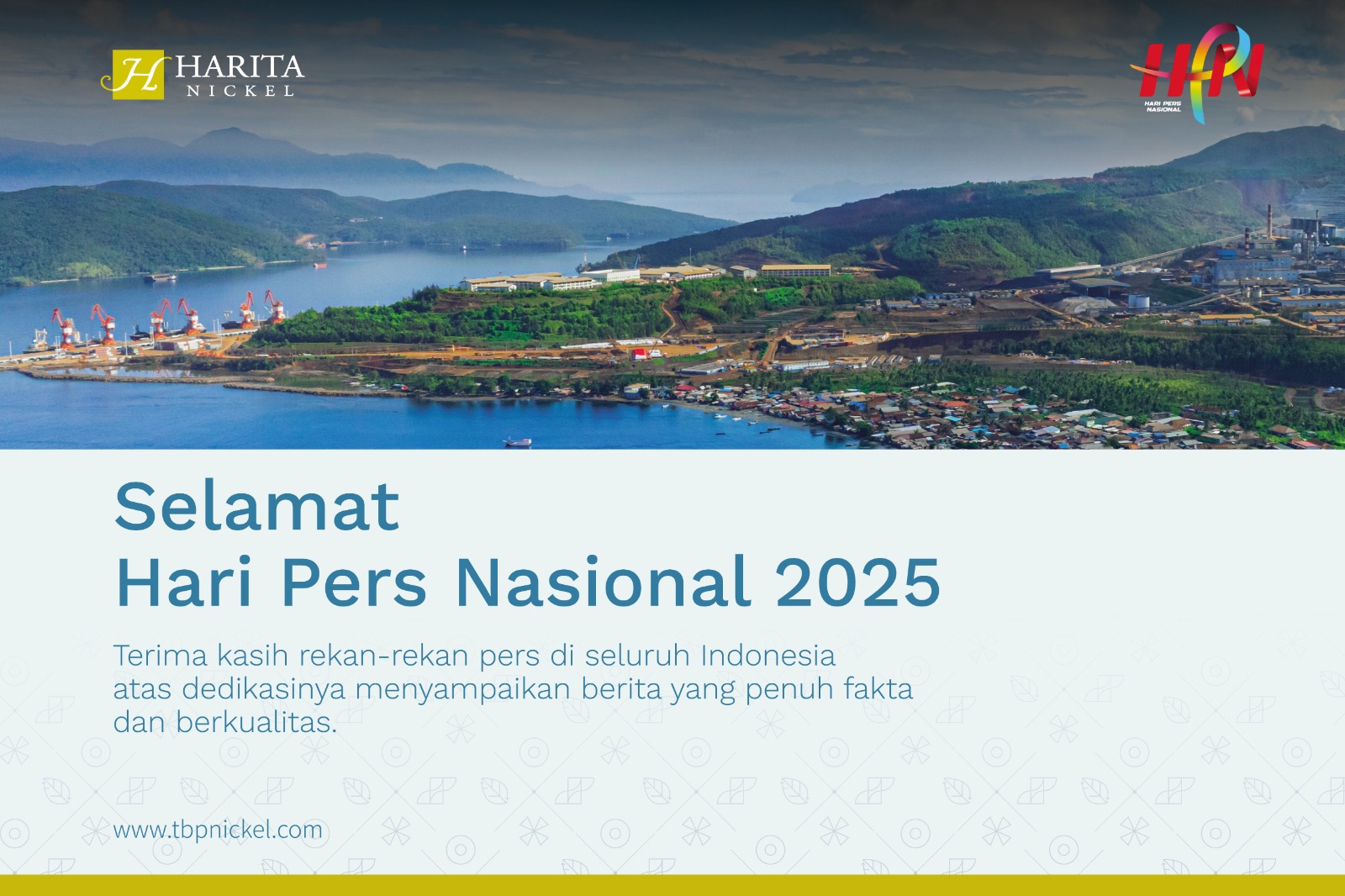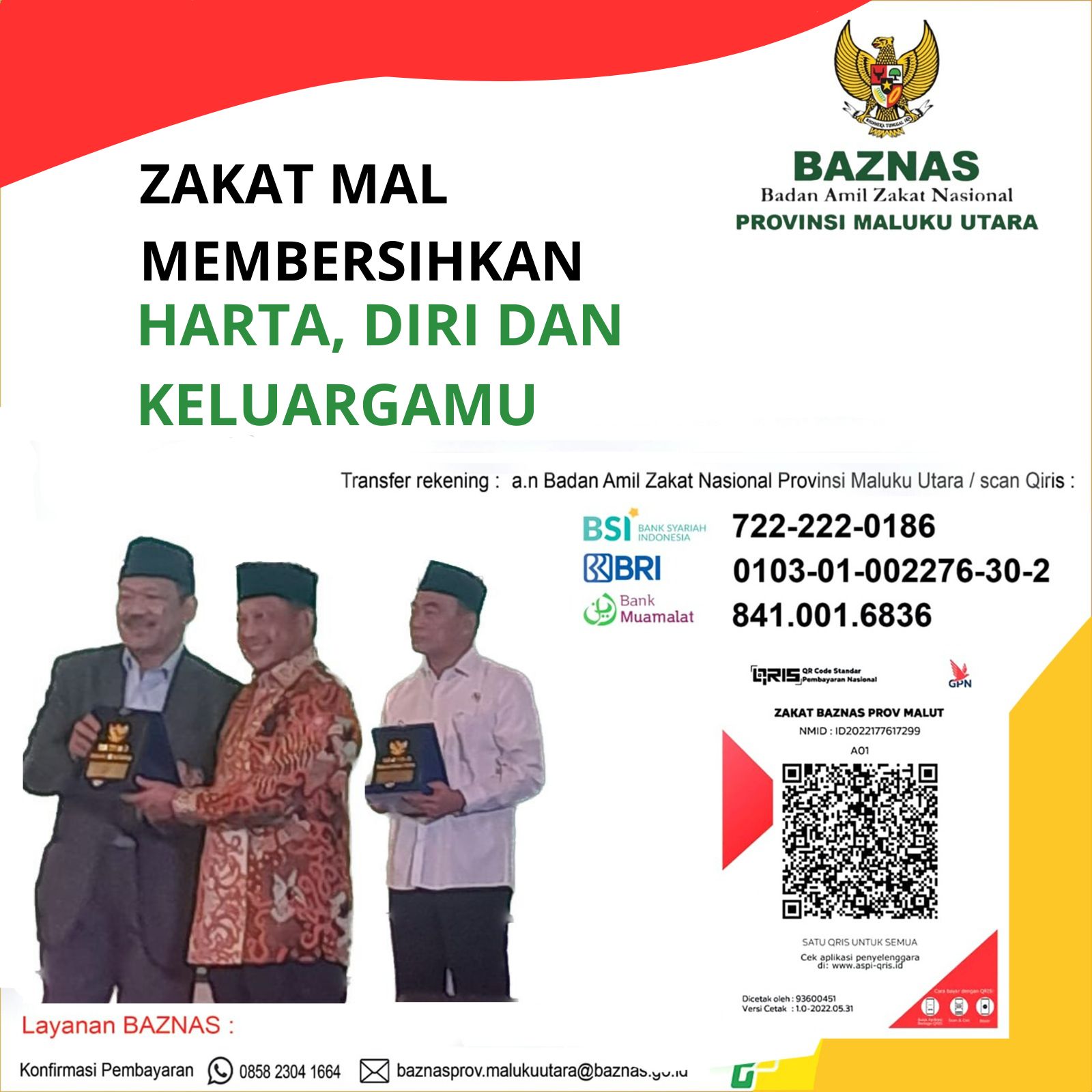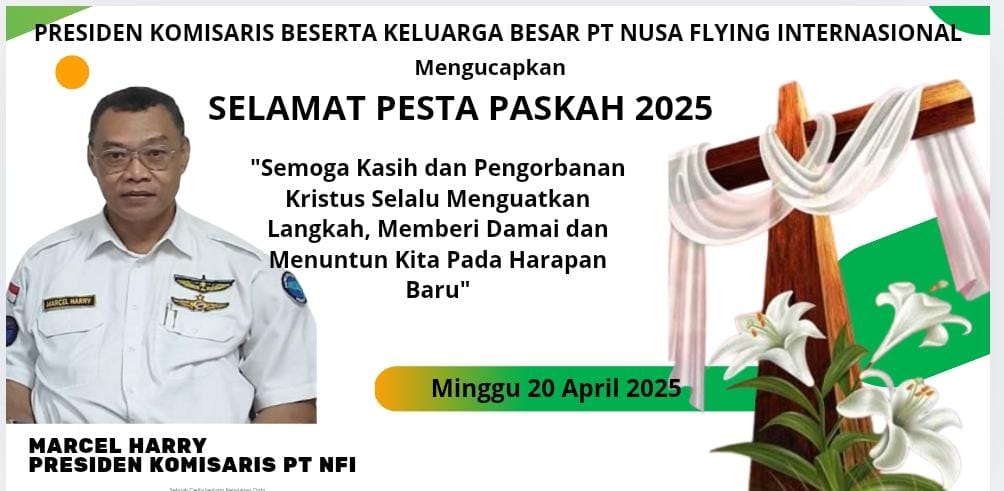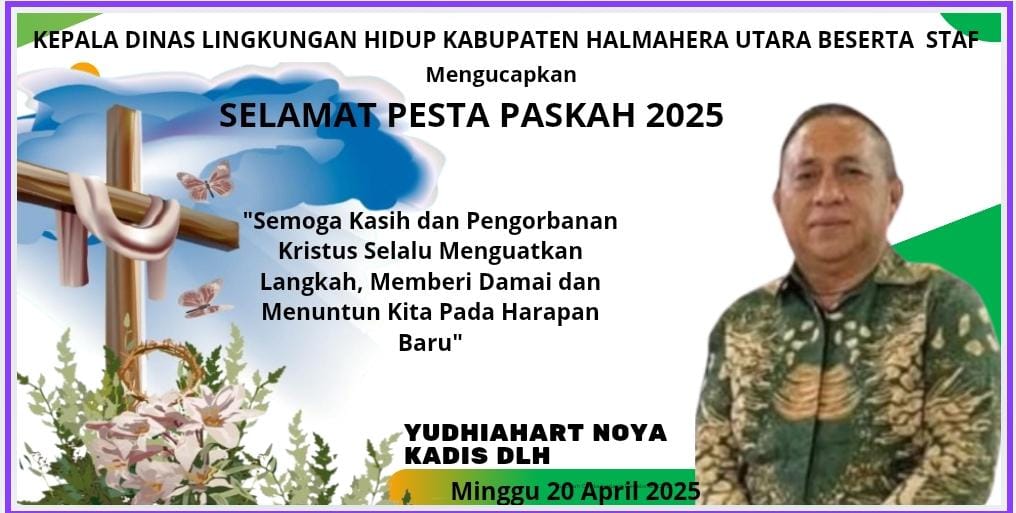CITA-cita luhur founding fathers untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa, merupakan impian kolektif yang tertuang dalam konstitusi. Keadilan sosial dan ekonomi bukan sekadar jargon, melainkan fondasi dari kontrak sosial antara negara dan rakyatnya.
Dalam idealnya, negara hadir sebagai fasilitator yang memastikan distribusi sumber daya alam dan ekonomi berlangsung merata, melindungi yang lemah, dan memberantas segala bentuk penyelewengan yang menghambat tercapainya kemakmuran bersama. Namun, jalan menuju cita-cita tersebut ternyata terjal dan dipenuhi dengan ujian-ujian berat.
Pemerintahan baru telah berupaya untuk menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi melalui penguatan institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan. Berbagai operasi tangkap tangan (OTT) dan proses hukum terhadap para koruptor dari level rendah hingga tinggi hal ini perlu diapresiasi. Walaupun upaya tersebut seringkali dinilai belum maksimal. Yang lebih memperparah situasi adalah kekacauan narasi yang kerap ditampilkan oleh perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian. Tidak jarang, pernyataan pejabat justru melukai perasaan dan mencederai logika masyarakat yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kekacauan narasi ini menunjukkan dua masalah mendasar, pertama, lemahnya koordinasi dan penyelarasan komunikasi antar-kementerian. kedua, dan yang lebih berbahaya, adalah indikasi bahwa sebagian elit pemerintah telah kehilangan kepekaan sosial. Mereka gagal memahami bahwa dalam situasi ekonomi yang tidak menentu dengan tingkat pengangguran yang membludak, setiap kata yang keluar dari mulut pejabat publik akan disaring melalui lensa penderitaan rakyat. Kata-kata yang terkesan ringan dan tidak baik bagi mereka, bisa menjadi percikan api bagi kemarahan rakyat yang sudah lama tertimbun.
Salah satu contoh narasi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang menimbulkan kontroversi adalah pernyataan mengenai penyitaan tanah yang dianggap menganggur, menyebutkan bahwa “seluruh tanah di Indonesia adalah milik negara” dan masyarakat hanya “menguasai”. Pernyataan awalnya yang disampaikan dalam konteks guyonan itu dinilainya tidak tepat dan tidak pantas disampaikan seorang pejabat publik, dan pada akhirnya diklarifikasi “bahwa konteks pernyataannya adalah menanggapi rencana penyitaan tanah Hak Guna Usaha (HGU) yang ditelantarkan, dan menegaskan bahwa tanah masyarakat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tidak akan terdampak kebijakan tersebut. Ia sepakat bahwa negara berperan sebagai penguasa sumber daya untuk kemanfaatan rakyat, bukan sebagai pemilik mutlak (Lestari, 2025).
Meskipun pada akhirnya pernyataan ini ditarik kembali, wacana yang muncul sesungguhnya mengandung nilai baik jika penerapannya adil dan jelas, yang patut dikaji lebih dalam jika nanti kemudian diterapkan. Ide ini sebenarnya adalah upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan tanah agar memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi rakyat.
Prinsip ini sesungguhnya telah memiliki preseden sejarah yang gemilang dalam masa Keemasan Islam. Khalifah Umar bin Khattab RA, misalnya, menerapkan kebijakan terhadap tanah hasil rampasan perang. Alih-alih membagikannya langsung kepada para prajurit, beliau menahannya sebagai aset bersama (milik negara) untuk kemudian dikelola dan hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyat, termasuk generasi mendatang (Janwari, 2016). Tanah-tanah itu disewakan kepada yang mampu mengelolanya, dan hasil sewa (tanah kharja) tersebut masuk ke Baitul Mal (kas negara) untuk membiayai pembangunan, jaminan sosial, dan kebutuhan publik lainnya (Chamid, 2010).
Kebijakan ini memperkuat perekonomian secara keseluruhan karena memastikan tidak ada sumber daya yang menganggur dan hasilnya dinikmati secara kolektif, pemikiran ini juga searah dengan pemikiran Muhammad Baqir ASH Shadr dalam Buku Induk Ekonomi Islam: IQTISHADUNA dimana dijelaskan lebih rinci mengenai tanah hasil rampasan perang, reklamasi, tanah yang diperoleh dari dakwah atau pernyataan kesediaan wilayah akan bergabung dengan kekuasaan Islam, dan tanah yang subur paska penaklukan adalah tanah yang akan dikelola oleh negara sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Shadr, 2008). Namun jika kebijakan penyitaan tanah nganggur ini tidak sesuai dan apalagi tidak menyentuh kepentingan publik sebagaimana yang dimaksudkan pada pemikiran Baqir ASH Shadr diatas maka sudah sepantasnya ditinjau kembali.
Penerapan prinsip ini di Indonesia modern memerlukan catatan yang sangat tegas dan berimbang. Kebijakan penyitaan atau pengambilalihan tanah tidak boleh menjadi alat bagi negara untuk sewenang-wenang terhadap hak milik rakyat, karena sengketa lahan berkepanjangan di Indonesia menyebabkan adanya aturan kepemilikan pribadi atas tanah. Sehingga definisi “menganggur” harus sangat jelas dan mempertimbangkan konteks lokal sehigga tidak menyebabkan bias pada penerapannya.
Sebagaimana di Maluku Utara, tanah dari Halmahera sampai Taliabu yang telah memiliki nilai ekonomi dan budaya, merupakan bagian dari siklus pertanian tahunan maupun bulanan sebagaiman cengkeh di Taliabu, pala dan coklat di Halmahera seharusnya tidak menjadi masalah pertanahan lagi, dimana konflik lahan sering menggerogotinya sebab telah adanya sertifikat menjadi simbol kepemilikan pribadi (Wardoyo, 2024).
Oleh karena itu, jika suatu tanah masih menunjukkan tanda produktivitas serta tanda kepemilikan (sertifikat), seperti adanya tanaman yang dirawat dengan alasan apapun, maka tanah tersebut harus dilindungi. Fungsinya harus diperkuat sesuai potensi awalnya, bukan dialihkan untuk kepentingan industri ekstraktif seperti pertambangan. Peran pemerintah justru seharusnya membangun industri pendukung yang memperkuat ketahanan pangan dan nilai tambah dari kekayaan lokal tersebut, misalnya dengan membangun pabrik pengolahan hasil pertanian atau pasar modern yang mempertemukan petani langsung dengan konsumen, dengan kata lain mendatangkan berbagai investor dan membuat Gudang untuk menampung hasil pertanian kita. bukan menggantinya dengan tambang yang justru sering merusak lingkungan dan mata pencaharian berkelanjutan.
Dengan kata lain tambang yang telah terlanjur beroperasi silahkan beroperasi dengan tanggung jawab sosial dan tetap menjaga serta sesuai dengan pemetaan kawasan yang suatu saat tidak merugikan masyarakat, apalagi sampai harus meninggalkan tanah kelahirannya hanya karna alasan pengelolaan kekayaan bumi. Karna pengelolaan kekayaan bumi pada prinsipnya untuk memastikan keberlanjutan kehidupan manusia bukan malah sebaliknya.
Krisis narasi dan kebijakan berpotensi merugikan rakyat ini diperparah oleh dua fenomena lain yang semakin menggerus kepercayaan publik, maraknya praktik pemalsuan (oplosan) dan perilaku para wakil rakyat yang tidak mencerminkan aspirasi konstituennya.
Praktik oplosan, dari minyak goreng, BBM, beras, hingga biskuit balita, adalah kejahatan yang sangat keji dan mencerminkan bobroknya moralitas ekonomi. Tindakan ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga membahayakan nyawa dan kesehatan publik. Maraknya praktik ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di sektor peredaran barang. Dalam situasi ekonomi yang sulit, di mana daya beli masyarakat melemah, permintaan terhadap barang murah meningkat, dan celah untuk praktik kriminal seperti ini semakin terbuka. Ini adalah bentuk nyata ketidakadilan yang dirasakan langsung oleh rakyat kecil.
Di level yang lebih tinggi, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat seharusnya menjadi penyalur aspirasi dan pengawas pemerintah. Namun, yang sering kali ditampilkan di media justru adalah pertunjukkan kekayaan dan gaya hidup mewah yang tidak mencerminkan penderitaan rakyat. Respon mereka terhadap isu-isu sensitif seringkali menggunakan bahasa yang tidak objektif, defensif, dan arogan. Alih-alih menjadi penenang, pernyataan mereka justru kerap menjadi bensin yang memicu kebakaran sosial.
Kombinasi dari semua faktor kebijakan yang tidak empatik, ketidakadilan ekonomi, kejahatan pangan, dan perilaku oknum elit yang tidak empati yang kemudian memicu ledakan amarah masyarakat. Keresahan yang sama dirasakan oleh banyak orang dari berbagai latar belakang, dari buruh, petani, hingga kelas menengah perkotaan. Keresahan bersama ini kemudian menjadi perekat, “semen sosial” yang menguatkan solidaritas di antara mereka. Kemarahan yang terakumulasi itu menemukan salurannya, baik melalui unggahan media sosial yang viral, demonstrasi di jalanan, atau bentuk-bentuk perlawanan sosial lainnya. Ini adalah alarm keras bagi negara bahwa kontrak sosial sedang berada di ujung tanduk.
Mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa memerlukan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Diperlukan pendekatan yang holistik, adil, dan berperspektif kerakyatan. Sebab pertumbuhan ekonomi harus merata, tidak hanya pada beberapa kelompok saja.
Dengan Langkah-langkah diantaranya Pertama, pemerintah harus mereformasi komunikasi kebijakannya. Setiap pernyataan haruslah lahir dari proses riset dan empati yang mendalam, bukan dari kesan serampangan.
Koordinasi antar-kementerian harus diperkuat untuk menciptakan narasi yang tunggal, jelas, dan menenangkan. Kedua, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, termasuk tanah, haruslah berpijak pada prinsip keadilan dan keberlanjutan. Negara bisa mengadopsi spirit dari kebijakan ekonomi Islam klasik yang mengutamakan kemaslahatan umat, tetapi dengan instrument hukum modern yang melindungi hak-hak masyarakat adat dan petani kecil. Penguatan industri lokal dan ketahanan pangan harus menjadi prioritas utama, bukan eksploitasi sumber daya alam yang masif dan merusak. Ketiga, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, tidak pandang bulu, dan konsisten.
Mulai dari koruptor kelas kakap hingga pelaku pemalsuan produk pangan, harus dihukum seberat-beratnya untuk menciptakan efek jera dan memulihkan kepercayaan publik. Dan terakhir, yang paling penting, para elit politik dan wakil rakyat harus melakukan introspeksi mendalam. Mereka harus kembali kepada fungsi dan tugas konstitusionalnya: melayani rakyat. Perilaku yang arogan dan tidak mencerminkan penderitaan rakyat hanya akan memperdalam jurang pemisah.
Dari tekanan publik yang begitu besar memaksa kekuatan politik untuk mengambil langkah-langkah korektif, bukan lagi sekadar pernyataan permintaan maaf. Dalam perkembangan yang cukup mengejutkan sekaligus memberi secercah harapan, para ketua partai mengambil tindakan tegas, dengan diberhentikan dari posisinya diantaranya Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya (Kompas, 2025). dan Adies Kadir (CNN, 2025) yang diakui memberi pernyataan kontroversi. Pemecatan ini jelas merupakan sebuah langkah politik yang tegas.
Langkah ini kemudian disusul dengan konferensi pers Presiden yang patut diapresiasi, dimana Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahnya untuk menghormati kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak fundamental rakyat, yang dilindungi oleh hukum internasional dan nasional, seperti UU No. 9 Tahun 1998 (Sumantri, 2025). Namun, pemerintah membedakan dengan tegas antara penyampaian aspirasi yang murni dan damai dengan aksi yang anarkis, mengganggu ketertiban, serta merusak fasilitas umum. Terhadap tindakan anarkis yang melanggar hukum, negara akan hadir secara tegas untuk melindungi keselamatan dan keamanan rakyatnya.
Presiden juga menekankan prinsip transparansi dengan memerintahkan proses hukum yang cepat dan terbuka terhadap oknum petugas yang diduga melakukan pelanggaran dalam menangani aksi unjuk rasa, menunjukkan komitmen untuk menjaga akuntabilitas aparat negara.
Tentunya dalam hal ini penjarahan adalah langkah yang keliru apalagi telah menyentuh hal yang sifatnya privasi, walaupun mungkin situasinya sangat tidak terkontrol dan tak tertebak sehingga kemarahan publik yang tak terbendung lagi sebab banyaknya permasalahan sosial dan ekonomi yang selama ini menghantui bangsa Indonesia.
Kadang memang kebebasan berekspresi itu menyentuk ranah etik, “sebagai contoh seseorang tidak mungkin memutar musik diantara keheningan tetangganya sampai larut malam, kecuali dalam hajatan tertentu” sejalan dengan Ketika rakyat menyampaikan kebebasan berekspresinya lalu dibalas dengan kebebasan ekspresi yang dilakukan oknum anggota DPR memiliki konsekuensi logis bahwa “kebebasan seseorang memang dibatasi oleh kebebasan orang lain” (Tarigan, 2018). maka dengan kata lain bahwa kebebasan itu tidak dibatasi oleh hal apapun kecuali kebebasan itu sendiri.
Ledakan amarah masyarakat adalah sebuah tanda bahwa masih ada harapan untuk berubah. Semen sosial yang menguat dari bawah tersebut adalah modal berharga untuk membangun Indonesia yang lebih adil. Tugas negara adalah merangkul solidaritas ini, mendengarkan keluhannya, dan mengubahnya menjadi kebijakan yang transformatif. Hanya dengan demikian, cita-cita masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa bukan lagi sekadar mimpi, tetapi suatu keniscayaan yang sedang diperjuangkan bersama. Selanjutnya kawal selalu apa yang telah disampaikan Presiden sebagai acuan perjuangan dan tentunya do’a terbaik kita untuk para pejuang yang jadi korban saat demonstrasi.(*)
Referensi
Chamid, N. (2010). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.
CNN. (2025). Adies Kadir Dinonaktifkan sebagai Anggota DPR. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250831172340-32-1268525/adies-kadir-dinonaktifkan-sebagai-anggota-dpr
Janwari, Y. (2016). Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer.
Kompas. (2025). 4 Anggota DPR Dinonaktifkan Partainya: Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya. Kompas.Com. https://nasional.kompas.com/read/2025/08/31/17162841/4-anggota-dpr-dinonaktifkan-partainya-sahroni-nafa-urbach-eko-patrio-uya
Lestari, L. (2025). Kronologi Pernyataan Nusron Wahid soal Tanah Telantar. Tempo.Co. https://www.tempo.co/politik/kronologi-pernyataan-nusron-wahid-soal-tanah-telantar-2058467
Shadr, M. B. A. (2008). BUKU INDUK EKONOMI ISLAM: IQTISHADUNA. zahra.
Sumantri, A. (2025). Presiden Prabowo Meminta Penyampaian Aspirasi Dilakukan dengan Damai. Metrotvnews.Com. https://www.metrotvnews.com/read/kj2CEY9m-presiden-prabowo-meminta-penyampaian-aspirasi-dilakukan-dengan-damai
Tarigan, A. A. (2018). Nilai-Nilai Dasar Perjuangan. Simbiosa Rekatama Media.
Wardoyo, H. (2024). Syarat Sah Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Kewenangan dalam Penerbitan Sertifikat Tanah di Indonesia Legal Requirements for Ownership of Land Rights and Authority in Issuing Land Certificates in Indonesia. Jurnal Kolaboratif Sains, 7(1), 119–129. https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4714.(*)