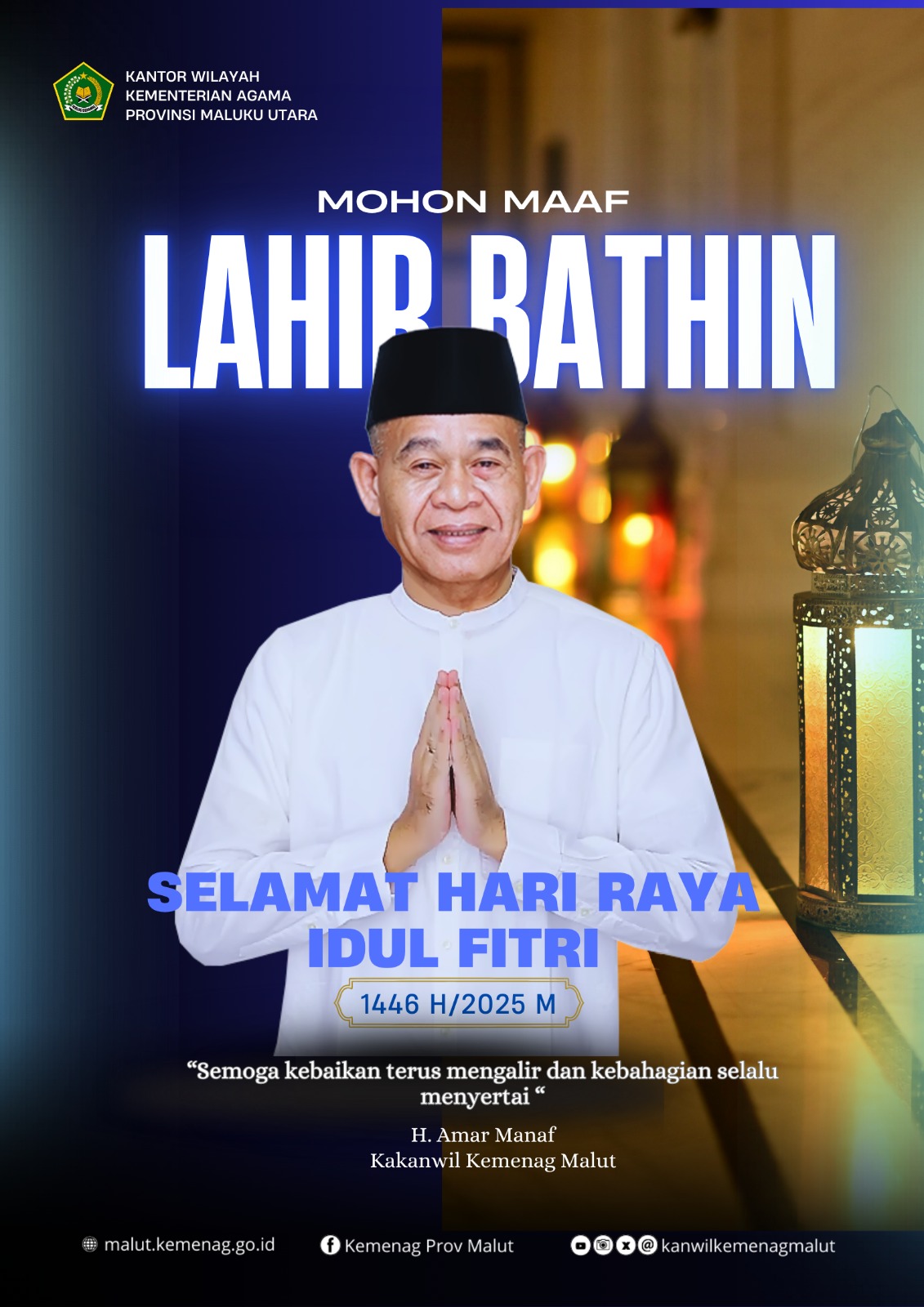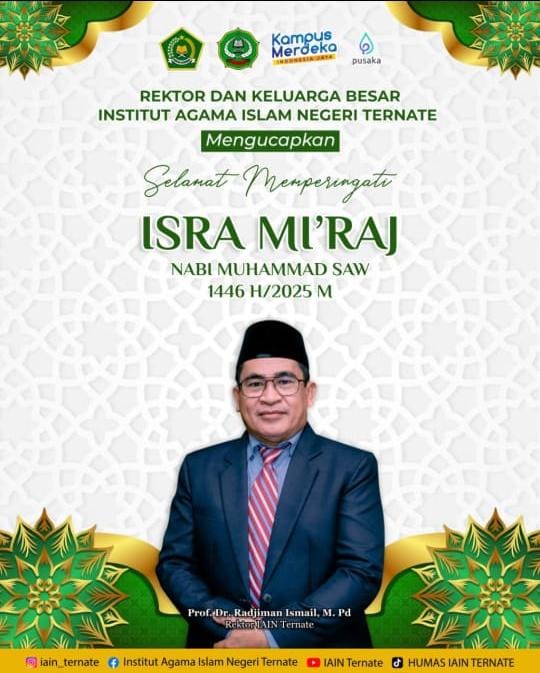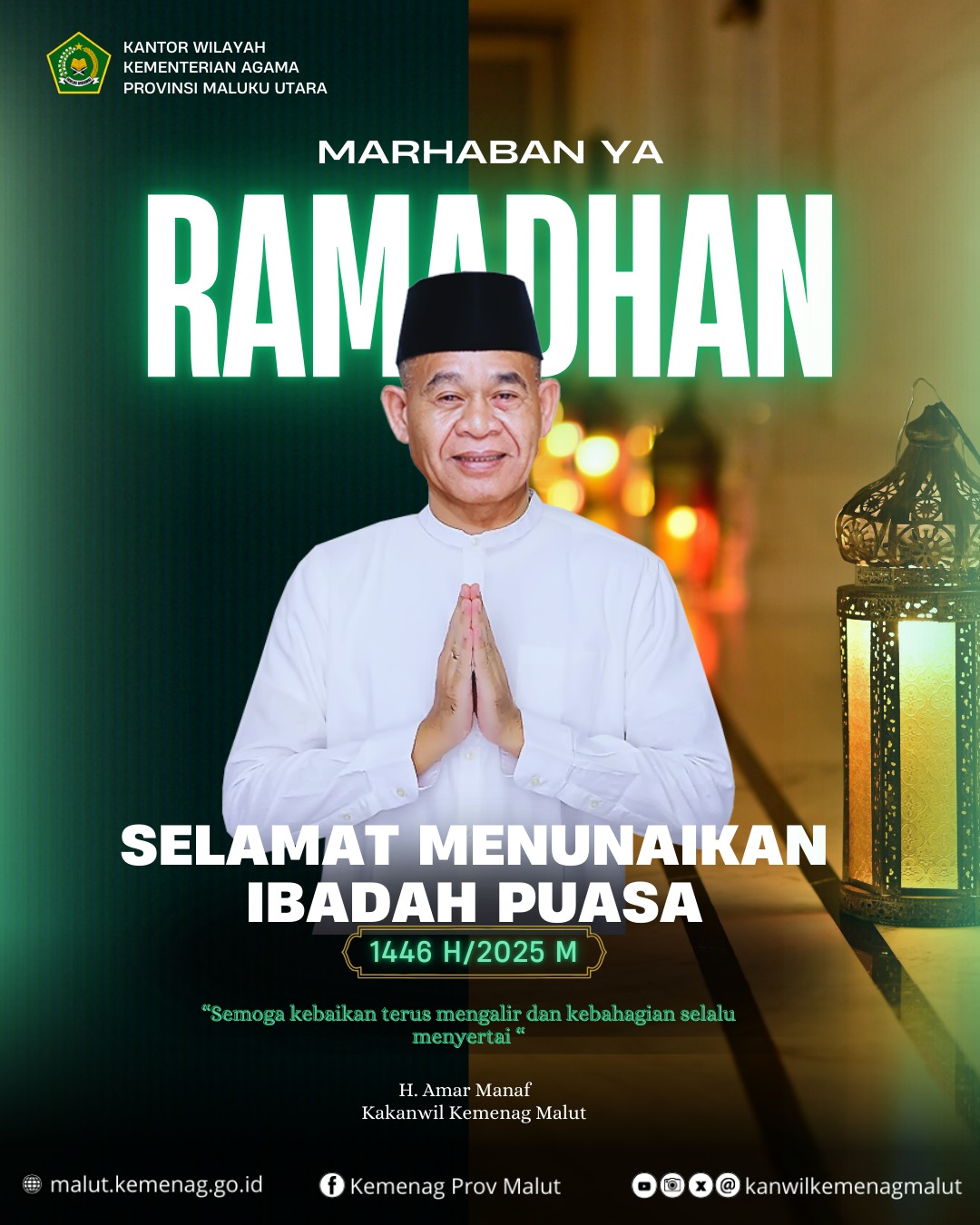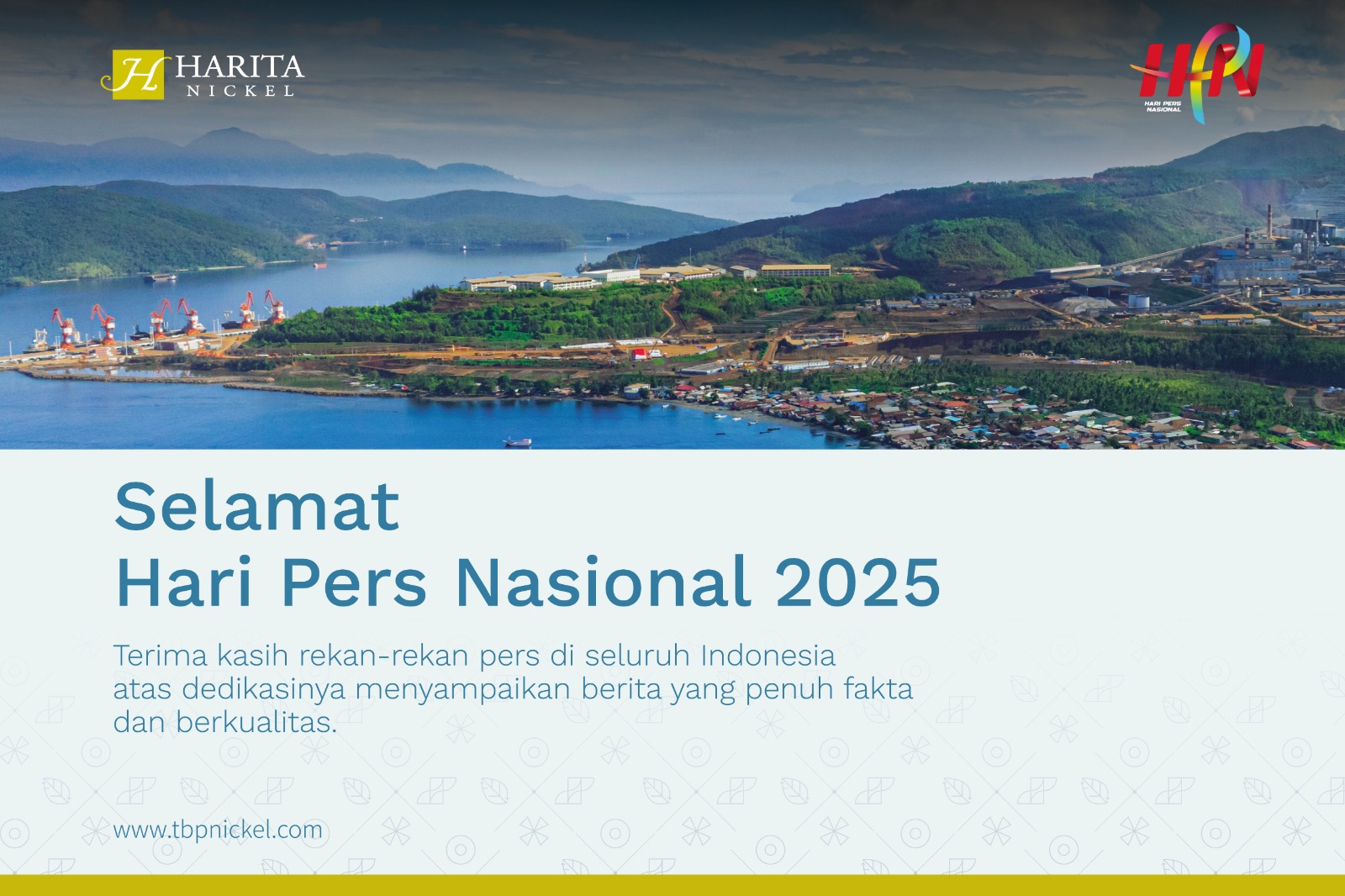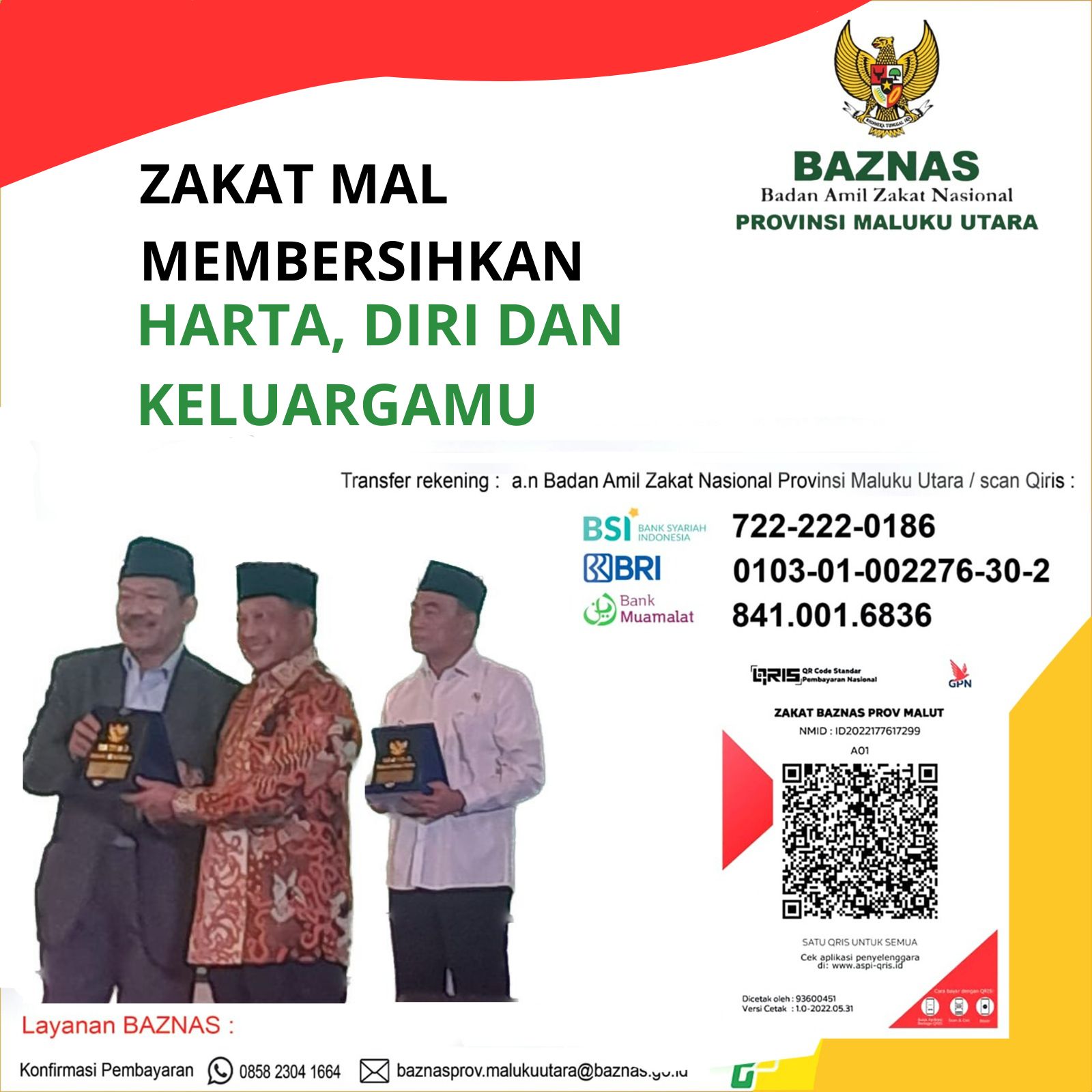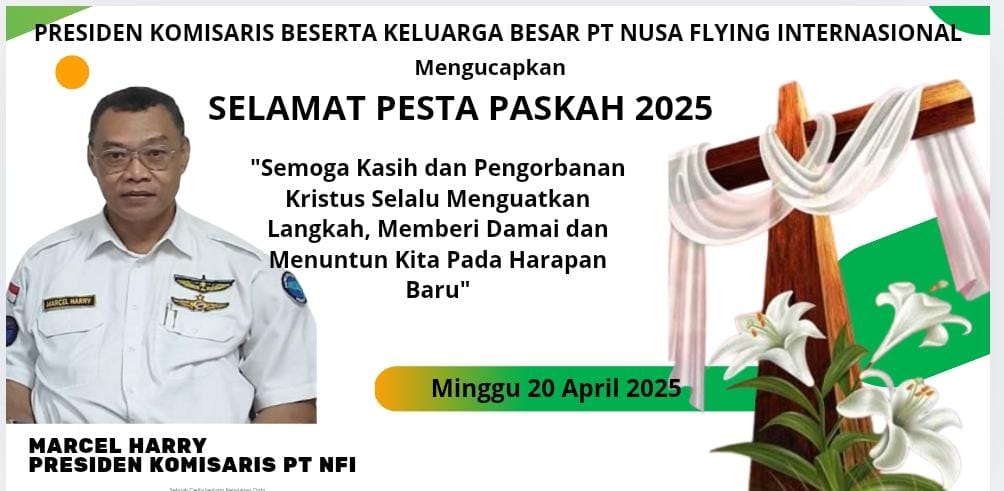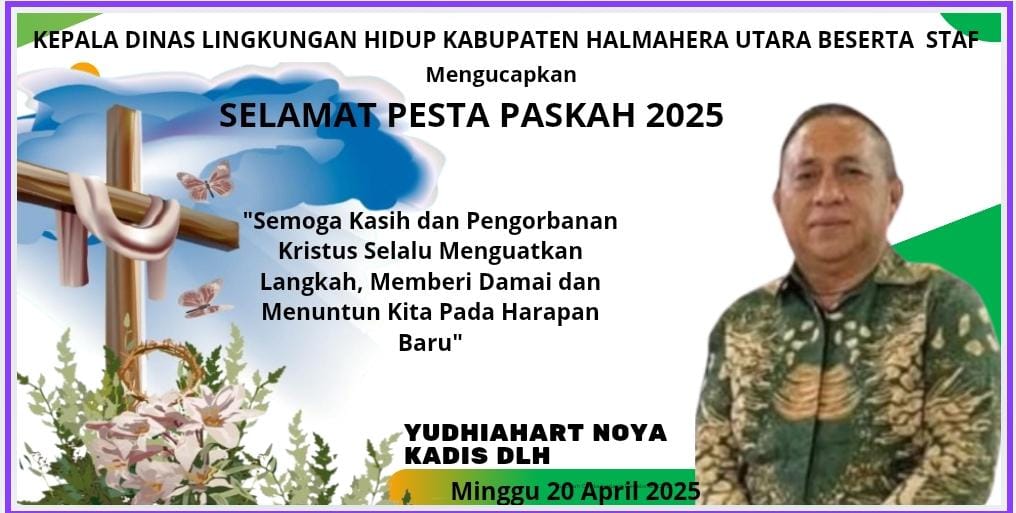KOTA TERNATE adalah salah satu Kota di Provinsi Maluku Utara yang terletak di kaki Gunung Gamalama, menghadapi paradoks pembangunan yang khas daerah kepulauan.
Di balik pesona alamnya yang memikat dengan panorama laut dan gunung yang memesona, kota ini bergulat dengan masalah pengelolaan sampah yang semakin kompleks.
Setiap hari, 214,4 ribu penduduk Ternate menghasilkan tidak kurang dari 120 ton sampah per hari dengan tingkat pengelolaan yang belum optimal karena masih menggunakan metode lama (Togubu, 2025).
Ironisnya, dikutip dari Yahya, (2024) komposisi sampah yang didominasi oleh bahan organik (80-90%) dan sisanya adalah merupakan sampah anorganik bernilai ekonomi (20-10%) justru menyimpan potensi ekonomi yang belum tergarap optimal.
Dalam konteks inilah, pendekatan pengelolaan sampah berkelanjutan tidak hanya menjadi solusi ekologis, tetapi sekaligus peluang emas untuk menciptakan lapangan kerja baru berbasis ekonomi sirkular.
Kondisi aktual pengelolaan sampah di Ternate menggambarkan situasi yang memprihatinkan. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berlokasi di Buku Deru-deru, Kelurahan Takome, Kecamatan Ternate Barat yang menjadi satu-satunya tempat pembuangan akhir memiliki potensi beroperasi melebihi kapasitas dengan sistem open dumping yang masih diterapkan.
Beberapa sumber menuliskan bahwa hanya sebagian kecil saja sampah yang terkelola dengan baik, sementara sisanya berakhir di badan air, pantai, atau dibakar secara sembarangan.
Padahal, komposisi sampah menunjukkan potensi ekonomi yang signifikan dimana 72 ton sampah organik harian yang dapat diolah menjadi kompos atau biogas, serta 36 ton sampah anorganik (plastik, kertas, logam) yang memiliki nilai jual di pasar daur ulang (Tidore, 2023).
Situasi ini mencerminkan paradoks dimana kota yang kaya akan potensi justru membiarkan sumber daya ekonomi terbuang percuma. Atau menurut saya, kenapa pemkot tidak menghadirkan industri baru di sektor pengolahan sampah? Karena ini merupakan masalah yang sudah terlalu berkepanjangan.
Bank sampah sebagai model partisipatif masyarakat menunjukkan potensi yang belum tergarap maksimal. Meskipun telah ada beberapa titik Bank Sampah di Ternate.
Sebagaimana Bank Sampah mandiri Cilacap membuktikan bahwa dengan insentif yang tepat seperti integrasi dengan sistem berbasis komunitas yang memungkinkan pemisahan sampah menjadi kategori seperti plastik, kertas, logam, dan organik.
Teknologi ini membuat proses daur ulang menjadi lebih efisien, Selain itu, Bank Sampah Unit Mandiri juga menerapkan teknologi komposting dalam mengolah sampah organik menjadi pupuk yang berguna bagi masyarakat.
Dengan kapasitas pengelolaan yang tinggi, bank sampah ini mampu memproses lebih dari 20 ton sampah setiap bulan. Seluruh jenis sampah ditangani secara terorganisir, mulai dari tahap pengumpulan hingga proses daur ulang.
Sehingga dari model diatas akan meningkatkan partisipasi masyarakat mencapai 70%. Untuk konteks Ternate, model ini perlu dikembangkan dengan beberapa inovasi: (1) digitalisasi transaksi melalui aplikasi mobile, (2) integrasi dengan program bantuan sosial pemerintah, dan (3) penciptaan pasar tetap untuk produk daur ulang.
Dengan pendekatan ini, bank sampah tidak hanya menjadi solusi pengelolaan sampah, tetapi juga wahana pemberdayaan ekonomi masyarakat akar rumput. Tentunya pemerintah harus mendukung penuh aktifitas ini.
Industri kreatif berbasis daur ulang di Ternate memiliki potensi yang baik namun masih menghadapi kendala skalabilitas. Seperti yang dilaksanakan oleh CSR AFT Babullah bersama Kelompok Ika Mario dimana menyulap sampah plastik menjadi batu bata, paving block dan batu angin bernilai tambah. Namun, produksi masih bersifat sporadis dengan keterbatasan akses pasar (Maluku, 2025).
Studi kasus dari Denpasar Bali menunjukkan bahwa nilai ekonomi produk daur ulang bisa meningkat ketika dikombinasikan dengan nilai seni dan cerita lokal. Untuk itu, diperlukan intervensi strategis berupa:
(1) pembentukan pusat pelatihan daur ulang terpadu, (2) pengembangan merek kolektif produk daur ulang khas Ternate, dan (3) integrasi dengan sektor pariwisata sebagai produk oleh-oleh, dengan hasil kreatifitas dari sampah plastik berupa tas belanjaan, keranjang, pot bunga dan bisa dijadikan sebagai wadah tanaman hidroponik.
Dengan dukungan penuh, industri ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja. Dengan kata lain masyarakat juga sudah semestinya mengubah cara pandangnya bahwa kita tidak mesti malu mengenakan produk dari hasil kreatifitas dari sampah.
Pengolahan sampah organik menawarkan peluang yang belum banyak dieksplorasi. Sampah organik bisa menjadi basis pengembangan industri pengomposan dan biogas skala komunitas. Model yang bisa dikembangkan adalah pembentukan unit pengolahan di setiap kelurahan.
Hasil kompos dapat dipasarkan ke perkebunan cengkeh dan pala yang menjadi komoditas unggulan Maluku Utara. Untuk sampah organik pasar tradisional, teknologi biogas skala menengah dapat menghasilkan energi listrik untuk kebutuhan fasilitas publik.
Transformasi pengelolaan sampah menghadapi tantangan perubahan perilaku masyarakat. Banjir yang dibarengi dengan tumpukan sampah di kota Ternate menunjukkan bahwa penduduk masih membuang sampah sembarangan.
Untuk mengatasi ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup: (1) integrasi pendidikan lingkungan dalam kurikulum sekolah, (2) kampanye media kreatif berbasis budaya lokal, dan (3) pembentukan kader lingkungan di setiap RT.
Perubahan sebagaimana yang dijelaskan diatas membutuhkan waktu dengan membiasakan masyarakatnya dahulu, tetapi sekali terbentuk akan menjadi budaya yang langgeng. Sehingga pentingnya ekonomi sirkular diimplementasikan di kota Ternate.
Ekonomi sirkular merupakan pendekatan yang menekankan pengurangan limbah dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, berbeda dengan model ekonomi linier tradisional yang mengandalkan pola “ambil, buat, buang”.
Dalam sistem ini, produk dirancang agar tahan lama, mudah diperbaiki, dapat digunakan kembali, dan akhirnya didaur ulang untuk memperpanjang siklus hidup (Lcdi, 2024). Penggunaan bahan baku juga diarahkan pada material yang terbarukan atau dapat didaur ulang guna menjaga nilai ekonominya dalam jangka panjang.
Prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang bertujuan untuk mengurangi limbah, menggunakan kembali produk, dan mendaur ulang bahan menjadi landasan utama untuk mendorong efisiensi dan pengelolaan limbah secara bertanggung jawab (Umumsetda, 2023).
Kolaborasi multipihak menjadi kunci keberhasilan transformasi ini. Kerangka kerjasama yang bisa dibangun meliputi: (1) sinergi pemerintah daerah dengan Universitas untuk penelitian dan pengembangan teknologi, (2) kemitraan dengan dunia usaha dan (3) pemberdayaan komunitas melalui pendampingan teknis..
Dalam perspektif jangka panjang, pengelolaan sampah berkelanjutan di Ternate berpotensi menjadi model nasional untuk daerah kepulauan. Keunikan geografis Ternate sebagai kota pulau justru menjadi laboratorium alami untuk mengembangkan model pengelolaan sampah yang adaptif dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Jika berhasil, model ini tidak hanya akan mengubah Ternate menjadi kota bersih, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana ekonomi sirkular dapat menjadi penggerak pembangunan inklusif.
Ternate saat ini berada pada titik balik penting. Di satu sisi, akumulasi sampah yang terus meningkat mengancam keberlanjutan ekologis dan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, terdapat peluang besar untuk mengubah tantangan ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru.
Pilihan ada di tangan seluruh pemangku kepentingan, apakah akan membiarkan sampah terus menjadi beban, atau mengubahnya menjadi berkah bagi kesejahteraan masyarakat.
Seperti kata pepatah, “Dalam setiap kesulitan terdapat peluang.” Untuk Ternate, peluang itu ada dalam tumpukan sampah yang selama ini dianggap sebagai masalah. Saatnya kita menulis babak baru dalam sejarah Ternate, dimana sampah tidak lagi menjadi momok, tetapi berubah menjadi berkah bagi kemakmuran bersama.(*)